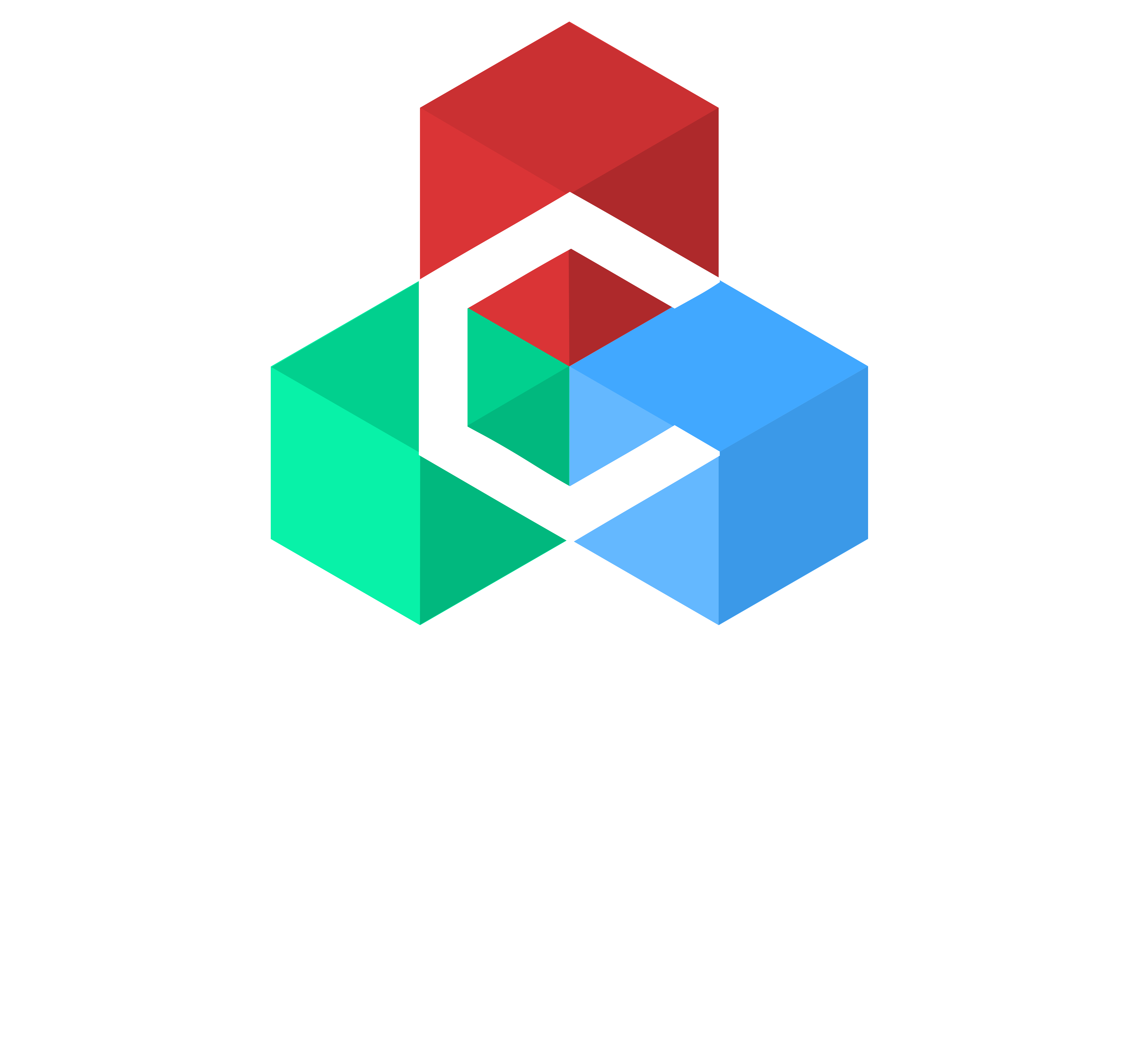Berburu dan mengumpulkan satwa liar di wilayah Papua khususnya yang tinggal berdekatan dengan hutan merupakan aspek penting bagi kehidupan masyarakat pedalaman. Hal ini karena berburu adalah salah satu cara untuk menyambung hidup. Kegiatan ini disebabkan karena terbatasnya akses masyarakat terhadap protein hewani yang diperoleh dari hasil peternakan. Di sisi lain, melimpahnya sumber makanan asal satwa liar adalah alasan utama bagi masyarakat lokal untuk berburu atau memanen satwa liar.
Satwa liar yang diburu masyarakat lokal umumnya bervariasi bergantung pada jenis hewan yang ada di sekitar hutan maupun wilayah pemukiman. Salah satu burung di Papua yang telah lama dimanfaatkan oleh masyarakat lokal adalah burung Maleo gunung (Aepypodius arfakianus). Burung Maleo gunung seperti jenis megapoda umumnya merupakan satwa yang unik, salah satunya dalam perkembangbiakkannya. Telur burung Maleo gunung tidak ditetaskan oleh induk burung sendiri, tetapi diletakkan pada tumpukan serasah dedaunan yang sumber panas berasal dari dekomposisi mikroba (Dekker dkk, 2000).
Burung maleo gunung ini biasanya tersebar di berbagai wilayah di kawasan konservasi Cagar Alam Pegunungan Arfak (CAPA) yang memiliki luas 68,325 hektar. Tidak hanya itu, Kampung Sigim dan Sinaitousi merupakan kawasan yang paling banyak ditemukan sarang burung Maleo gunung (Manik dkk, 2018). Umumnya mereka adalah Suku Hatam yang telah lama memanfaatkan burung megapoda sebagai sumber pangan maupun menambah pendapatan keluarga secara turun temurun, tingginya permintaan ini tidak terlepas dari kebutuhan pangan asal satwa liar khususnya ukuran daging dan telur burung Maleo gunung yang relatif besar (Manik dkk, 2015).
Suku Hattam di Kampung Sigim, Sinaitousi Syoubri dan Kwau sudah mengenal burung Maleo gunung secara turun temurun. Artinya, pengetahuan ini merupakan warisan dari leluhur mereka yang mendiami daerah tersebut. Nama lokal burung tersebut dalam bahasa Hatam adalah sumuga, ada juga yang menyebut semuwa/smuwa, smu, semubwa, smugbwa dan smowa.
Perburuan burung dan pemanenan telur burung Maleo gunung merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Suku Hattam secara turun temurun. Pengetahuan teknik berburu burung dan pemanenan telur dengan menggunakan peralatan tradisional merupakan bagian dari kearifan lokal masyarakat suku Arfak untuk menjaga keberadaan burung ini di alam.
Pengetahuan kearifan masyarakat lokal dalam perburuan burung maleo gunung yaitu kemampuan masyarakat berburu untuk mengetahui jejak kaki burung secara visual dan melihat tanda-tanda disekitar habitat seperti jenis pohon atau tanaman tertentu,bekas makanan dan kotoran sehingga memudahkan mereka memasang jerat atau perangkap tampa memasang umpan. Pengetahuan kearifan masyarakat lokal untuk mengetahui musim berkembangbiak (breeding season) burung Maleo gunung. Menurut masyarakat suku Arfak, musim bertelur burung dalam satu tahun terjadi dua kali yaitu musim Po ba dan Wap ngat.
Musim Po ba atau Matoa ditandai dengan beberapa fenomena alam terutama pada tumbuhan. Masyarakat suku Arfak mengetahui musim bertelur burung Maleo gunung dengan melihat tanda-tanda alam pada tanaman pohon matoa (Pometia pinnata) atau bahasa Hattam disebut Po ba. Warna bunga matoa umumnya hijau kekuningan sedangkan warna buah bervariasi dari warna hijau hingga unggu dengan ukuran panjang buah sekitar 1,5-5 cm dengan diameter 1-3 cm. Ketika pohon ini berbunga, merupakan petunjuk bagi masyarakat Suku Hattam bahwa burung maleo gunung akan bertelur sehingga satu atau dua bulan selanjutnya mereka dapat memeriksa sarang burung untuk memanen telur yang ditinggalkan pada sarang burung yang berukuran besar. Umumnya, burung maleo membuat sarang dengan ukuran sarang 1,5 – 2 m dengan tinggi sarang 0,8-1 m, jumlah telur bervariasi dari 5 hingga 10 telur per sarang.
Menurut masyarakat suku Hattam, musim Po ba merupakan waktu bertelur burung yang relatif pendek (short season). Musim ini umumnya terjadi pada bulan Juni sampai Juli (dua bulan). Dengan periode bertelur (clutch) yang pendek maka jumlah telur yang didapat relatif sedkit sehingga seringkali Suku Hattam tidak banyak memanen ke hutan di wilayah kampungnya.
Berbeda dengan musim Po ba, pada musim Wap ngat atau Litsea masyarakat Suku Arfak khususnya Kampung Sigim dan Sinatousi mengetahui musim bertelur atau berkembangbiak dengan melihat tanda-tanda alam utamanya pohon Litsea (Litsea ledermanii) atau bahasa lokal suku Hatam disebut wap ngat. Biasanya, warna bunga kuning dan buah pada waktu muda berwarna hijau, sedangkan ketika sudah tua berwarna unggu, dan ukuran panjang buah 0,5-1 cm. Ketika pohon litsea mulai berbunga maka biasanya bagi masyarakat lokal hal ini merupakan penanda akan dimulainya musim berkembangbaik. Pada saat musim berbunga maka hutan disekitar areal hutan biasanya menjadi berwarna kekuningan sehingga mudah untuk dilihat dari kejauhan. Periode ini induk jantan segera menyiapkan sarang untuk betina bertelur. Bentuk sarang yang besar seperti gunung api dan sekitar areal sarang yang bersih dari dedaunan memudahkan pemburu mengetahui lokasi persarangan.
Menurut masyarakat suku Hattam, musim wap ngat merupakan musim panen telur berlimpah (long season). Musim ini biasanya terjadi pada bulan Nopember hingga Februari. Periode bulan ini biasanya curah hujan di Papua Barat paling tinggi sehingga jenis pohon buah-buahan yang ada di hutan akan banyak berbuah dan ketersedian pakan burung melimpah. Pada periode ini, burung Maleo gunung akan bertelur cukup lama (tiga bulan), periode bertelur (clutch) sehingga masyarakat lokal akan mengumpulkan telur yang banyak untuk dikonsumsi atau dijual.
Bagi masyarakat Suku Arfak khususnya Suku Hattam, biasanya mereka cukup merapikan kembali sarang yang telah digali atau dipanen telurnya sehingga burung akan kembali bertelur pada periode tahun berikutnya. Pada umumnya masyarakat suku ini tidak mengambil telur yang “sudah tua” atau embrio anak burung telah tumbuh. Biasanya masyarakat Suku Hatam membedakan telur berdasarkan warnanya. Warna telur “baru” dan “lama“ dapat dikenali dengan melihat warna telur yang “lama” terlihat putih pucat dan telur “baru” terlihat putih mengkilap.
Masyarakat Arfak sebenarnya secara adat telah memiliki konsep pengelolaan kawasan yang dikenal dengan ‘Igya Ser Hanjop.” Penerapan sistem ini karena adanya pemahaman dan kesepakatan masyarakat untuk penetapan beberapa wilayah sebagai kawasan konservasi. Kawasan konservasi terdiri dari 3(tiga) zona yaitu Bahamti (kawasan konservasi), Nimahanti (kawasan terbatas/penyangga) dan Susti (wilayah pemanfaatan), masyarakat Suku Hattam memanen hanya pada wilayah pemanfaatan atau wilayah adat kampung mereka sendiri.
Salah satu bentuk pemanfaatan satwa liar oleh masyarakat asli Papua adalah melalui kegiatan perburuan untuk kebutuhan konsumsi dan praktek sosial budaya masyarakat yang merupakan tradisi turun temurun, kondisi ini umum ditemukan dalam kehidupan masyarakat di daerah pedalaman Papua. Sejalan dengan hal diatas desentralisasi pemerintahan dari pusat ke daerah maka implikasinya adalah adanya pemekaran kampung/desa, pembukaan jalan, pembukan lahan pertanian, perumahan menyebabkan areal habitat burung Maleo gunung makin menyempit. Pembukaan akses transportasi dari kota ke kampung yang semakin mudah juga berdampak dengan semakin konsumtif masyarakat lokal akan kebutuhan ekonomi menyebabkan eksploitasi sumber daya alam semakin tinggi.
Kontrol pemuka adat atau kepala suku dalam pemanenan telur di habitat asli untuk tujuan pemanfaatan perlu mendapat perhatian sehubungan dengan usaha konservasi dan pemenuhan kebutuhan manusia. Strategi pemanenan berkelanjutan dalam rangka pelestarian alam dengan membuat berbagai program inovatif agar penghasilan dari alam (khususnya wisata kehidupan liar) dapat digunakan untuk mengelola satwa liar dan ekosistemnya sebagai sumber daya alam setempat yang dapat mendatangkan keuntungan bagi masyarakat setempat.
Juara Harapan 2 Essay Contest 2020
Penulis: Hotlan Manik
Penyunting: Rosyid Amrulloh