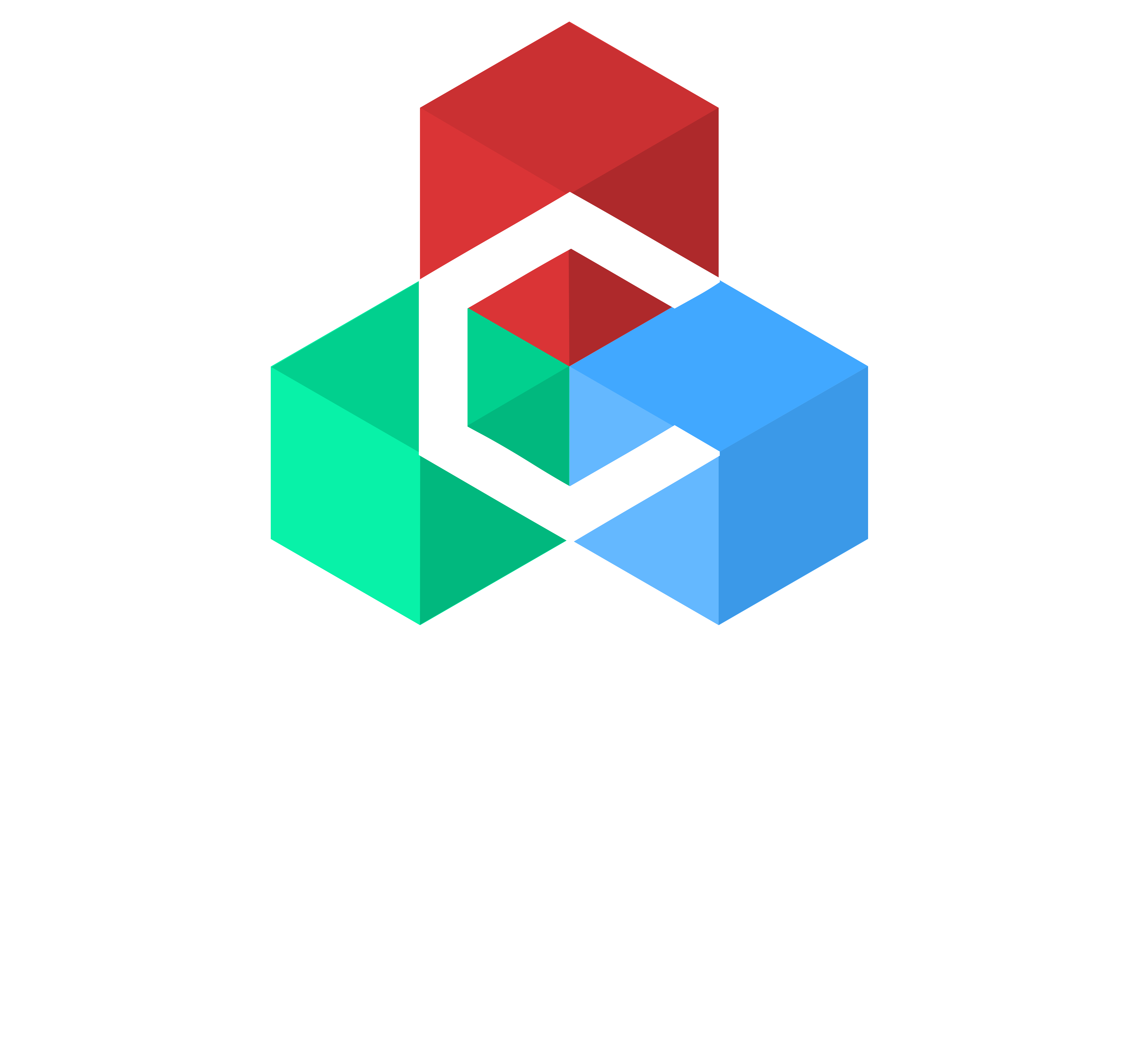Sering kali, kita berhadapan dengan kenyataan yang kompleks; bahkan jauh berbeda, dengan konsep atau rencana yang telah disepakati sebelumnya. Sebagai contoh, mungkin kita bisa melihat seperti apa pembangunan yang diorientasikan di wilayah Papua. Namun, apakah dinamika ini bersifat mutlak adanya? Pertama, kita harus memahami lapisan imajinasi dan realitas bagi seorang individu. Seperti yang pernah dikatakan oleh Albert Einstein (1879-1955), imajinasi lebih penting ketimbang pengetahuan karena sifatnya yang tak terbatas. Ia tidak sekadar energi yang menggerakkan, tetapi juga mampu melahirkan kemajuan evolusi.[1]
Di samping itu, salah satu filsuf modern dalam aliran filsafat voluntarisme etis, Schopenhauer (1788-1860), mengatakan bahwa realitas adalah segala yang dirasakan dunia dalam ruang dan waktu, apa yang tampak terjadi; terikat dengan hukum kausalitas. Menurut Schopenhauer, tatanan realitas yang ada pada dunia, dihidupi oleh kehendak sebagai daya pendorong seluruh aktivitas kehidupan. Kehendak diyakini tidak hanya sebagai penggerak bagi manusia untuk berpikir dan bertindak, melainkan juga penggerak bagi unsur elementer dalam tubuhnya, dari keadaan yang tak sadar menjadi setengah sadar, dan seterusnya.[2]
Bagi pendekatan transdisipliner, ada keterbukaan mendasar dalam realitas yang ikut melibatkan keterbukaan akan masa depan. Kita adalah bagian yang berjalin-kelindan dalam realitas. Kebebasan kita pun menyatu dalam suatu gerakan; atau bahkan mengganggunya di sisi lain. Kita bisa merespon gerakan atau memaksakan kehendak kita akan kekuasaan dan dominasi. Tanggung jawab kita adalah untuk membangun masa depan yang berkelanjutan, sesuai gambaran umum akan realitas. Dan transdisipliner menunjukkan sebuah jalan yang realistis untuk membangun masa depan tersebut.[3]
Nicolescu mengajukan tiga pilar dalam transdisiplinaritas. Pertama, epistemologi yang dipahami sebagai pengetahuan yang muncul, kompleks. Kemudian, realitas (ontologi), yang dimaksud sebagai kenyataan multilevel; perspektif dan sudut pandang dunia, yang dimediasi oleh Yang Tersembunyi (the Hidden Third), serta logika simpulan yang disebut sebagai logika jalan tengah; ruang antar-disiplin ilmu dan antara akademia dan masyarakat.[4] Ia pun menjelaskan bahwa transdisiplinaritas menghargai hubungan yang kompleks dan dinamis, di antara setidaknya 10 realitas berbeda yang diatur dalam tiga Tingkatan Realitas: (a) dunia internal manusia, di mana kesadaran mengalir – pada subjek transdisipliner (terdiri dari realitas politik, sosial, sejarah, dan individu); (b) dunia eksternal manusia di mana informasi mengalir – objek transdisipliner (terdiri dari realitas lingkungan, ekonomi, dan planet); serta (c) Yang Tersembunyi – pengalaman, interpretasi, deskripsi, cerita, representasi, gambar, dan formula lainnya bertemu di tahap ketiga ini. Tiga Tingkatan Realitas di zona intuitif non-resisten ini, berhadapan dengan budaya dan seni, agama, serta spiritualitas. Secara kolektif, ketiga tingkatan tersebut membentuk ontologi transdisiplinaritas; atau apa yang dikehendaki sebagai tujuan bersama.[1]
Dalam hal ini, pertemuan atau bahkan terbenturnya jalinan fakta dan realitas, membuat kita lebih sadar akan arti keberagaman. Seperti konteks dari masyarakat A, atau sudut pandang dari wilayah B, dan berbagai kemungkinan lainnya. Terlebih pandemi global saat ini tak jarang memperlihatkan ketimpangan yang begitu dekat. Sehingga situasi ini tidak hanya memunculkan keresahan bagi seluruh pihak, tetapi juga ikut menegasikan hak-hak dasar yang sepatutnya menjadi perhatian dan tanggung jawab negara. Belum lagi, realitas yang ikut “membanjiri” lini media massa hari ini, mulai dari yang terbukti dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT), menerima suap hingga miliaran rupiah, hingga sibuk melanjutkan proyek yang mencerabut ruang hidup warga.
Pada Agustus lalu, laporan dari Perkumpulan Advokat Hak Asasi Manusia (PAHAM) dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Papua menyatakan, ada 304 warga sipil; baik di Provinsi Papua maupun Papua Barat, yang telah menjadi korban dalam peristiwa kekerasan militer sepanjang Januari – Desember 2020. Dari 63 kasus kekerasan yang tercatat, 35 kasus di antaranya didorong oleh motif politik, dan diikuti oleh motif arogansi aparat sebanyak 25 kasus dan kekerasan bermotif ekonomi sebanyak tiga kasus.[2] Bukankah realitas demikian cukup menjadi bukti, bahwa kekerasan tidak akan pernah menyelesaikan akar persoalan yang terjadi; khususnya di Tanah Papua? Kita tak bisa terus memungkiri bahwa fakta dan jalinan peristiwa yang terjadi, turut memecah rasa persatuan yang ada. Getirnya pengalaman akan marjinalisasi, rasisme, eksploitasi, dan berbagai bentuk perampasan sumber daya lainnya, ikut membenarkan sebuah ungkapan “the paradox of plenty” atau paradoks berkelimpahan.
Namun, di balik ingatan kolektif masyarakat Papua atas penderitaan yang mereka alami, masih ada kesempatan untuk kita menyadari dan berdiskusi secara terbuka. Sebagai upaya dalam membangun kepercayaan, pendekatan humanistik yang dimungkinkan oleh transdisiplinaritas, turut membuka ruang yang mampu membaca fakta di balik “angka-angka”, mengangkat suara maupun opini minoritas, serta mengedepankan harkat, martabat, dan harga diri masyarakat Papua.
Selain itu, kita juga harus mulai memahami bahwa segala bentuk bayangan akan modernisasi, atau standar kesejahteraan yang kita miliki, tidak serta-merta sesuai dengan apa yang menjadi konteks kebutuhan masyarakat Papua. Sehingga kita harus senantiasa belajar untuk mendengarkan lebih dalam, melihat sudut pandang mereka, apa yang menjadi kebutuhan, serta bagaimana merangkul keberagaman dari memori kultural yang ada.
“Bagi Orang Papua, mungkin karena pengalaman sejarahnya yang getir, ada yang lebih berharga dari sekedar kesejahteraan material, yaitu martabat dan harga diri; dan itu yang selama ini diabaikan. Setelah Aceh, Papua adalah tes terakhir mampukah kita berdiri sebagai sebuah republik yang menghargai warga negaranya sendiri.”[1]
[1] Komlik, Oleg, “Albert Einstein on the Power of Ideas and Imagination in Science”, Economic Sociology (8 Januari 2016), https://economicsociology.org/2016/01/08/albert-einstein-on-the-power-of-ideas-and-imagination-in-science/.
[2] Munir, Misnal, “Filsafat Voluntarisme”, Jurnal Filsafat (Juli 1997) https://journal.ugm.ac.id/wisdom/ article/viewFile/31658/19189, p. 16.
[3] Nicolescu, B., “Transdisciplinarity and Sustainability”, TheATLAS Publishing (2012), p. VII.
[4] Ibid, p. 9.
[5] Ibid, p. 9-10.
[6] Mawel (2021) dalam Rakhman, Ode; Umi Ma’rufah; et al., “Laporan Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua”, #BersihkanIndonesia, YLBHI, et al. (12 Agustus 2021), p. 6.
[7] Tirtosudarmo, Riwanto, “Manuel Kaisiepo”, Kajanglako (26 Agustus 2019), https://kajanglako.com/id-8983-post-manuel-kaisiepo.html.