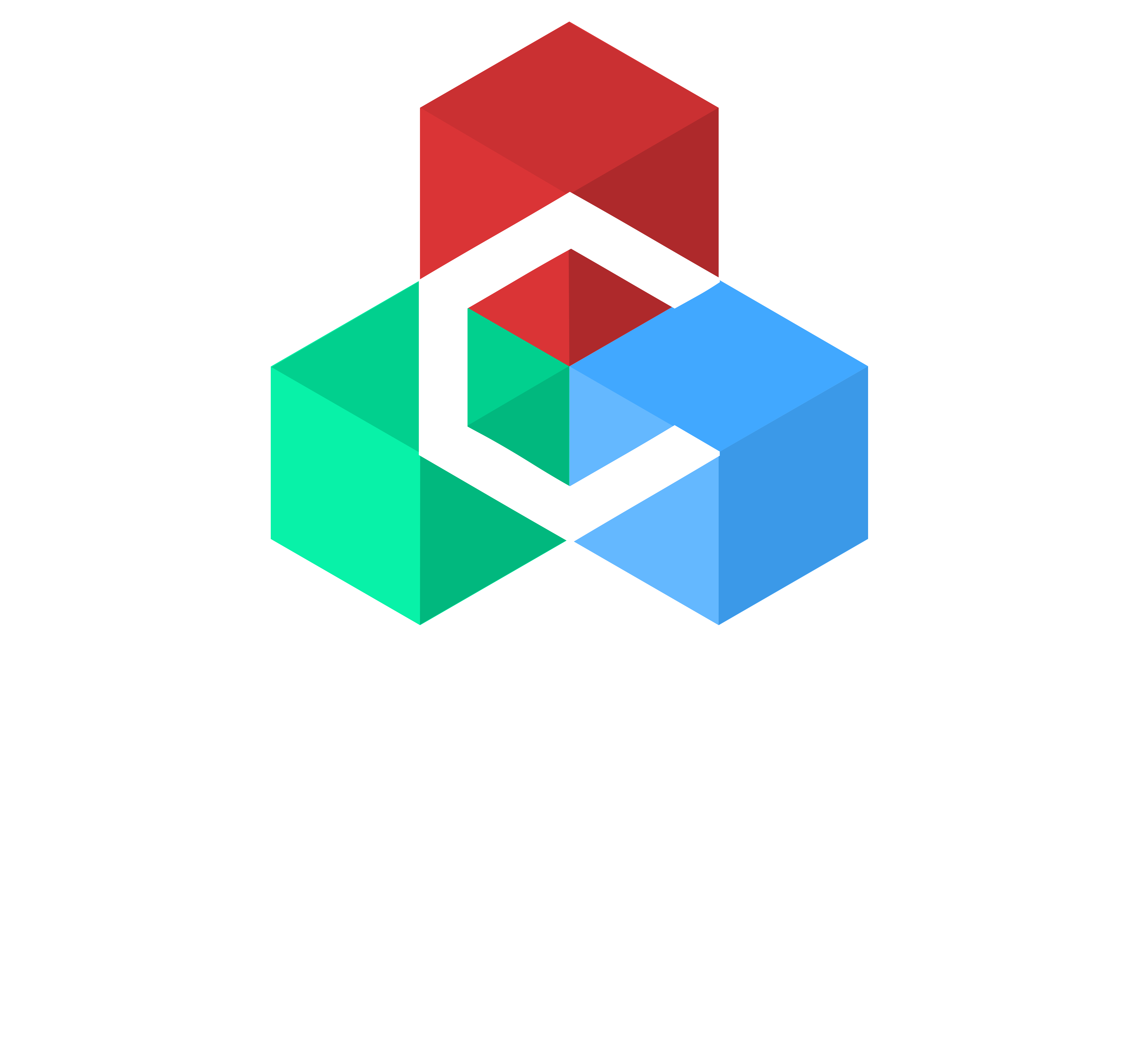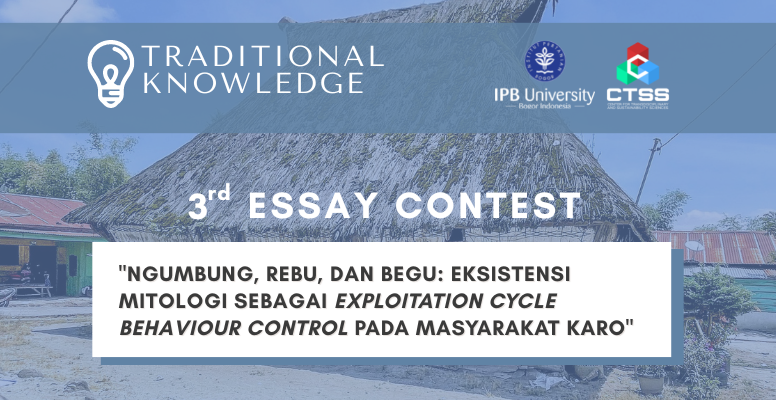Langit terlihat mendung dan gelap sejauh mata memandang, awan keabu-abuan menutupi area perladangan di suatu daerah di Pegunungan Bukit Barisan, Sumatera Utara. Waktu menunjukkan semakin petang dan matahari semakin tak memperlihatkan cahayanya. Sayup-sayup terdengar gemuruh menggelegar dari balik bebukitan. Tepat pukul lima sore, hujan rintik-rintik mulai turun dan membasahi tanah yang sudah tak menyisakan tanaman padi di ladang tersebut. Setelah tanah mulai sedikit basah, suara pet-pet atau tonggeret terdengar bersahut-sahutan. Sama seperti tadi pagi, hingga waktu petang, tak terlihat seorang pun di area perladangan yang berbukit tersebut, entah bekerja maupun melintas.
Perladangan yang sepi dan seolah-olah ditinggalkan tersebut menjadi pemandangan umum ketika masyarakat telah melaksanakan panen padi. Panen padi pada Masyarakat Karo mengikuti sistem kalender tersendiri. Masyarakat Karo menggunakan sistem kalender lunar yang bersumber dari gerak revolusi bulan. Kalender ini memiliki 30 hari dalam sebulan, yang disebut dengan Niktik Wari Si Telu Puluh. Setiap hari dari 30 hari tersebut memiliki makna masing-masing dan aktivitas komunal masyarakat mengacu pada arti hari-hari tersebut, salah satunya adalah Ngumbung.
Ngumbung adalah hari dimana masyarakat dilarang untuk menginjakkan kaki di tanah perladangan. Ngumbung dilaksanakan pada hari Cukera Enem Berngi, yaitu hari ke-enam dalam kalender Masyarakat Karo. Ngumbung dilakukan setelah masyarakat melaksanakan panen raya pada hari sebelumnya, yaitu hari ke-lima dalam kalender yang dikenal dengan nama Beraspati. Ngumbung sendiri adalah salah satu bagian dari sistem Rebu. Rebu dapat diartikan sebagai sesuatu yang tabu atau pantangan. Ngumbung sendiri memiliki makna sebagai Rebu Kujuma atau pantang mengunjungi ladang.
Ngumbung atau tabu untuk mengunjungi perladangan ini didasarkan pada cerita atau mitos. Mitos yang berkembang turun temurun mengisahkan bahwa pada hari ke-lima (Beraspati), masyarakat akan melaksanakan panen padi. Di hari ke-enam (Cukra Enem Berngi), maka giliran Begu atau roh-roh ghaib yang akan melaksanakan pekerjaannya. Oleh karena itu, selama Begu atau roh ghaib ini mengunjungi perladangan, manusia tidak boleh mengunjungi karena dapat berakibat buruk. Hal ini kemudian dikenal sebagai Rebu Sierdempaken atau pantang berhadapan/berpapasan. Dalam mitologi tersebut, dilanjutkan bahwa apabila manusia berhadapan atau berpapasan dengan Begu, maka roh manusia dapat ikut terseret ke alam ghaib.
Ngumbung sendiri tidak hanya dilaksanakan pada hari ke-enam atau pasca-panen padi, namun juga dilakukan pada beberapa hari lain pada bulan yang berbeda. Setidaknya Ngumbung dilakukan 6 kali selama siklus tanam padi, dan selama 6 kali tersebut pula masyarakat tidak mendatangi ladang karena adanya mitos atau cerita tentang begu tersebut. Selain pada proses tanam padi, konsep ngumbung dan begu ini juga terdapat dalam aktivitas lain, misalnya pembukaan lahan. Pembukaan lahan boleh dilakukan pada hari ke-limabelas yaitu Tula dan pantangan pembukaan lahan dilakukan pada hari sebelumnya yaitu Belah Purnama Raya. Masyarakat umumnya takut untuk melanggar rebu atau tabu tersebut mengingat hal buruk yang mungkin menimpa mereka.
Sekilas cerita atau mitos tentang ngumbung dan begu mungkin terdengar seperti isapan jempol belaka. Namun, cerita tersebut memiliki dampak yang panjang dalam membentuk pola atau gaya eksploitasi lahan yang dilakukan masyarakat Karo. Pola eksploitasi lahan yang dimaksud adalah adanya periode jeda atau diskontinu pada siklus penggunaan lahan. Walaupun mungkin leluhur masyarakat Karo tidak secara sadar menciptakan mitologi begu tersebut, namun ngumbung karena adanya begu memiliki ritme yang selaras dengan alam.
Sehari setelah proses panen padi biasanya banyak biji padi yang tertinggal, baik yang berjatuhan selama proses panen maupun yang tersisa pada tangkai padi. Ceceran biji padi ini akan mengundang burung karena biji padi menjadi makanan pokoknya. Selain itu, sehari setelah proses panen, ladang tersebut akan menjadi breeding ground banyak jenis serangga. Sedangkan tikus-tikus tanah akan mulai bermigrasi meninggalkan lahan karena mulai tidak adanya tanaman padi. Cara masyarakat tradisional membersihkan lahan pascapanen biasanya adalah dengan cara pembakaran jerami yang tersisa. Apabila pembakaran jerami ini dilakukan langsung setelah proses panen, serangga, burung dan tikus-tikus yang bermanfaat secara ekologis tersebut dapat musnah dalam sekejap. Oleh karenanya, adanya ngumbung tersebut memastikan tidak ada intervensi manusia selama proses ekologis tersebut berlangsung.
Selain pada hari ke-enam, ngumbung juga dilakukan pada hari pertama kalender, yaitu pada hari Aditia. Sehari sebelumnya yaitu pada hari ke-tigapuluh (Sami Sara), terjadi akhir siklus revolusi bulan yang ditandai dengan bulan mati atau bulan tidak terlihat. Selama bulan mati, banyak jenis burung dan serangga yang kawin dan berkembang biak di perladangan. Biasanya telur-telur serangga dan sarang burung banyak di temukan di perladangan setelah bulan mati. Secara kebetulan, adanya mitos begu pada hari Aditia mampu mecegah intervensi manusia yang mungkin dapat mengganggu proses perkembangbiakan hewan-hewan tersebut.
Berbeda dengan hewan-hewan yang berkembang biak pada bulan mati di area perladangan masyarakat, banyak jenis hewan atau burung di hutan justru berkembangbiak pada saat bulan purnama. Pada tahap ini lah, mitos mengenai begu memiliki peran penting. Masyarakat Karo dilarang untuk membuka lahan di daerah hutan ketika hari Tula, yaitu hari ke-lima belas. Di hari sebelumnya yaitu Belah Purnama Raya, kemungkinan banyak jenis hewan dan burung yang berkembang biak dan menghasilkan telur di cabang-cabang pepohonan. Proses ngumbung pada hari Tula dapat memastikan bahwa burung-burung dapat bertelur setelah bulan purnama, tanpa takut diganggu oleh manusia.
Adanya ngumbung pada Masyarakat Karo karena mitos mengenai begu terbukti efektif dalam mengontrol perilaku masyarakat dalam eksploitasi lahan. Adannya jeda tersebut memberikan waktu bagi makhluk-makhluk lain untuk melakukan akvitas esensial mereka seperti kawin, menghasilkan telur maupun migrasi ke tempat baru karena hilangnya sumber makanan. Aktivits hewan-hewan tersebut digambarkan oleh leluhur sebagai begu atau roh ghaib yang mengunjungi perladangan dan dihindari untuk berpapasan. Mitos-mitos tersebut memastikan bahwa aktivitas ekologis hewan-hewan seperti serangga dan burung terjamin sehingga populasi mereka tetap terjaga.
Dewasa ini, masyarakat sudah meninggalkan sistem kalender lunar tersebut dan melupakan mitos-mitos yang dianggap takhayul. Akibatnya, lahan digunakan secara intensif dan kontinu tanpa jeda. Padahal, hal yang mendukung terjaganya relung ekologis dan populasi hewan selain makanan dana habitat adalah adanya waktu atau fase dimana aktivitas esensial mereka tidak diintervensi. Hal ini dapat diamati, dimana ekosistem dan populasi hewan yang konsisten selama berabad-abad mulai hilang karena masyarakat mengeksploitasi lahan tanpa jeda. Sistem kalender dan siklus jeda penggunaan lahan yang dilakukan oleh Masyarakat Karo sebenarnya dapat diadaptasi untuk membantu keberlanjutan ekosistem termasuk penjagaan populasi hewan-hewan yang hidup berdampingan dengan aktivitas manusia. Namun, selama masyarakat masih memanfaatkan lahan tanpa jeda dan tidak memberi ruang dan waktu bagi makhluk lain, mungkin kita tidak akan menyaksikan ekosistem sebagaimana Masyarakat Karo menyaksikan ekosistem mereka berabad-abad yang lalu.
Penulis: Edy Ridwanda
Juara 1 Kategori Umum