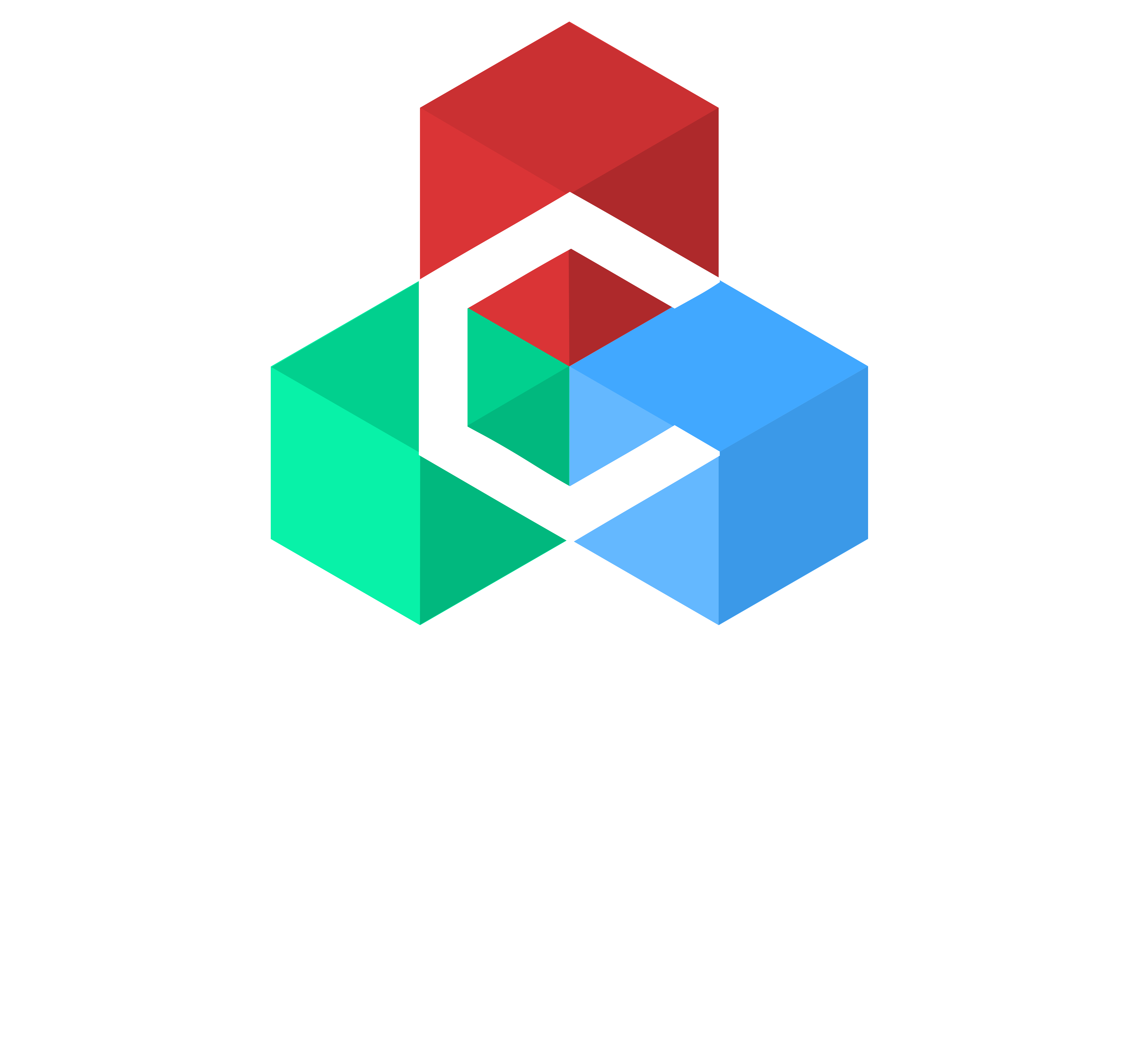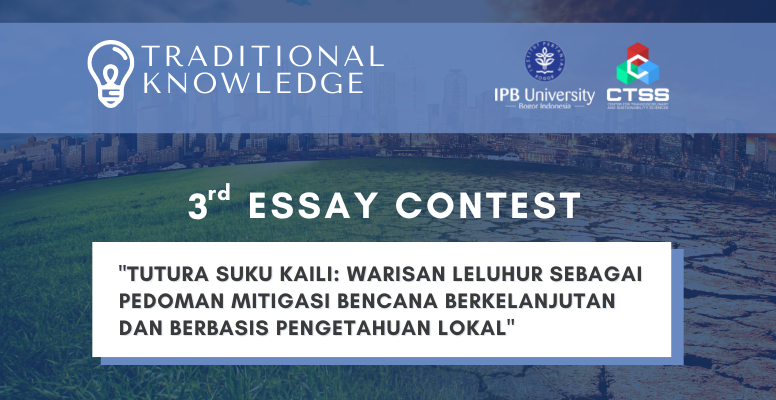Tidak ada satu orang pun yang akan mengangguk setuju ketika melihat keputusan janggal yang diambil sebuah keluarga saat bencana likuefaksi menerjang Desa Sibalaya Selatan, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Saat itu, bumi yang dipijak terasa berguncang hebat dan tanah bergulung menelan banyak bangunan. Namun, alih-alih mencari daratan luas tanpa ada bangunan yang berpotensi runtuh dan jatuh menimpa, mereka malah tergopoh-gopoh masuk rumah dan menutup pintu rapat-rapat. Keluarga ini telah melanggar segala bentuk panduan modern soal menyelamatkan diri saat likuefaksi, bahwa setiap orang harus berlari sejauh mungkin untuk sampai ke dataran batuan keras dan menjauhi permukiman padat.
Langit Sigi sore hari itu jadi saksinya. Likuefaksi terjadi begitu singkat dan tanpa aba-aba. Tanah Desa Sibalaya memang berpasir dan mudah diresapi air. Oleh karena itu, getaran gempa membuat tanah di daerah tersebut kehilangan ikatannya, tak lagi padat atau keras dan melarut seperti lumpur. Bagai gelombang raksasa, tanah di Desa Sibalaya Selatan bergulung tak karuan dan menyebabkan ribuan rumah runtuh. Sebagian besar masyarakat yang tidak sempat menyelamatkan diri seketika tertelan bumi. Sebelum menyadari apa yang terjadi, daratan telah terbelah, orang berlarian kalang kabut, sebagian besar bangunan hancur tak bersisa, sebagian yang lain digeser tanah dan tumpuk-menumpuk dengan bangunan lain. Saat tak ada lagi lipatan tanah yang bergerak, menyisakan hening, bingung, duka dan korban bergelimpangan di tengah masyarakat Sibalaya, kita akan terbelalak saat mengetahui nasib keluarga janggal tadi. Mereka yang berbuat tidak logis–masuk rumah dan menutup pintu di saat semua orang berlari sekencang mungkin untuk menyelamatkan diri–ternyata selamat tanpa kurang sedikit pun. Ketika guncangan berakhir, kebingungan menghinggapi keluarga tersebut saat menyadari bahwa desa luluh lantak, sebagian besar tetangga meninggal dan mereka menjadi satu-satunya keluarga yang selamat!
Tanggal 28 September 2018 menjadi memori atas tragedi dan kesedihan mendalam bagi bangsa Indonesia. Alam menerjang Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Donggala dengan tiga bencana sekaligus, yakni gempa bumi, tsunami dan likuefaksi. Gempa pertama melanda Kabupaten Donggala dengan kekuatan 6 Magnitudo pada pukul 14.00 dan menyebabkan 10 orang luka-luka. Tiga jam kemudian, saat masyarakat Palu sedang berkumpul di Pantai Talise untuk festival perayaan, gempa kembali mengguncang Kota Palu dan Donggala dengan kekuatan 7,4 Magnitudo. Jembatan Ponulele yang menjadi ikon Kota Palu patah. Kubah Masjid Baiturrahman roboh. Hotel Roa-roa runtuh menimbun banyak orang.Tak lama setelah gempa, tsunami dengan ketinggian 6 meter menerjang Pantai Talise. Menyapu habis bangunan dan orang di sekitar pantai. Orang-orang berteriak kalang kabut, menjerit kepanikan. Keesokan harinya, santer terdengar kabar ada tanah bergerak di Kabupaten Sigi. Bangunan dan pepohonan bergerak, saling menimbun di atas tanah yang menggulung bagai ombak. Gempa yang terjadi sebelumnya membuat ikatan tanah menjadi renggang. Hal tersebut menyebabkan tanah tercampur air dan bergetar bagai lumpur.
Akibat kejadian tersebut, BNPB mengungkapkan jumlah korban meninggal sebanyak 2.101 jiwa, korban hilang sebanyak 1.373 jiwa, luka-luka 4.438 jiwa, sebanyak 221.450 orang harus mengungsi di 122 titik pengungsian. Dampak kerugian ditaksir mencapai 2,89 triliun rupiah dengan dampak kerusakan sejumlah 15,58 triliun rupiah.
Sebelum Petaka
Fenomena likuefaksi di Palu semakin menjadi perbincangan banyak orang saat diketahui ada dua perumahan amblas. Perumnas Petobo dan Balaroa mendadak terbenam ke tanah sedalam 20 meter akibat likuefaksi. Tanah yang di atasnya didirikan perumnas tersebut seakan tak kuat menopang beban. Akibatnya, saat likuefaksi terjadi, ikatan tanah menjadi renggang sehingga menelan ratusan rumah yang ada di perumnas tersebut. Rumah dan bangunan yang ada pun seketika patah dan runtuh tak bersisa. BPBD mencatat setidaknya 900 keluarga ikut tertimbun di Perumnas Balaroa dan 744 unit rumah tertimbun lumpur di Perumnas Petobo.
Jauh sebelum kejadian perumnas amblas, sesepuh adat suku Kaili, suku asli daerah Palu dan sekitarnya, pernah memperingatkan untuk tidak melanjutkan pembangunan perumnas tersebut. Sesepuh adat tersebut bersikeras bahwa tanah yang akan dibangun perumnas di atasnya merupakan lokasi tempat hilangnya sapi-sapi raja dahulu kala. Dengan membangun perumnas di lokasi tersebut, sesepuh adat berdalih akan terjadi kejadian serupa seperti sapi-sapi raja yang ditelan bumi. Namun, karena dianggap hanya mitos dan takhayul semata, pembangunan tetap berlanjut. Pada akhirnya, semua mafhum bahwa kekhawatiran sesepuh adat yang semula dianggap takhayul terbukti. Cerita sesepuh adat menyatakan bahwa sapi-sapi raja yang hilang, pada akhirnya, ditemukan mati di laut Donggala oleh nelayan. Ratusan tahun setelah sapi raja raib tiba-tiba, ditemukan penjelasan bahwa di daerah Balaroa ada pusentasi atau pusat laut. Pusentasi adalah saluran air di bawah tanah yang langsung menuju laut. Saat gempa terjadi, ikatan tanah menjadi longgar karena air tersebut. Cerita takhayul oleh sesepuh menjadi logis saat perumnas yang amblas mengalami hal serupa dengan hilangnya sapi-sapi raja. Namun, sayangnya, semua terlambat.
Cerita rakyat semisal tadi merupakan salah satu kearifan lokal yang dimiliki oleh suku Kaili. Kearifan lokal tersebut dinamakan tutura yang berarti penuturan lisan. Kehidupan suku Kaili yang telah berjalan selama ratusan tahun memberi mereka memori kolektif yang diturunkan menjadi tutura yang terus direproduksi dari satu generasi ke generasi lain.
Salah satu bentuk tutura adalah toponimi daerah atau penamaan daerah. Pemberian nama tersebut dilatarbelakangi oleh peristiwa yang pernah terjadi di suatu daerah, termasuk kejadian bencana. Artinya, suku Kaili telah memahami daerah mana saja yang dalam sejarahnya pernah terjadi bencana dan menandai daerah apa saja yang rawan terjadi bencana berdasarkan penamaannya. Sebagai contoh, Desa Rogo, Kabupaten Sigi memiliki arti pernah hancur. Ratusan rumah kemudian hancur di desa tersebut pada saat bencana 28 September 2018 dan saat banjir bandang 2020. Kemudian ada Desa Beka, Kabupaten Sigi yang berarti pernah terbelah. Tanah di desa tersebut banyak terbelah saat likuefaksi September 2018. Lalu ada Desa Jono Oge, Kabupaten Sigi yang berarti banyak tumbuhan alang-alang. Tumbuhan jenis ini biasa tumbuh di sungai dan rawa-rawa. Namun, saat bencana September 2018, daerah tersebut bukanlah sungai atau rawa seperti yang tergambar dalam penamaannya, melainkan permukiman padat. Oleh sebab itu, Desa Jono Oge ikut terkena dampak likuefaksi. Masyarakat Kaili menilai dampak tersebut terjadi karena Desa Jono Oge dibangun di atas jalur air yang seharusnya tidak dijadikan permukiman.
Kearifan lokal tutura suku Kaili dapat menjadi mitigasi bencana yang efektif. Dengan memaknai penamaan tiap daerah dan menyesuaikan perilaku pembangunan di atasnya, tutura toponimi daerah seharusnya dapat berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs nomor 11 tentang permukiman berkelanjutan. Pola pembangunan yang sesuai dengan toponimi daerah dapat membantu mitigasi bencana, mengingat karakteristik wilayah dan kebencanaan yang berbeda di tiap daerah.
Kalaulah pembangunan dua perumnas tadi menaati larangan sesepuh adat yang berdasar tutura, mungkin tak ada kejadian ratusan rumah dan keluarga yang tertelan tanah. Semua menjadi logis dan tidak bernilai takhayul saat terbukti dengan jelas. Sebagai perbandingan, Kampung Tua Kinta menjadi satu-satunya kawasan dalam Kelurahan Petobo yang selamat saat likuefaksi menerjang. Sebaliknya, berhektar-hektar permukiman dalam satu kelurahan yang menjadi tetangganya hancur lebur tak bersisa. Bukan tanpa alasan, Kampung Tua Kinta memiliki arti tempat menetap atau tanah untuk rumah. Salah satu tutura yang masih lestari mengenai Kampung Tua Kinta adalah larangan kawasan tersebut ditempati oleh lebih dari 60 orang. Saat jumlah penduduk terus bertumbuh, Kampung Tua Kinta tetap menaati tutura dan selamat melewati likuefaksi.
Saat Bumi Berguncang
Banyak peristiwa terjadi dan terekam menjadi memori komunal yang diturunkan dari satu moyang ke moyang lainnya melalui tutura. Salah satu tutura yang terus direproduksi hingga hari ini adalah tutura soal pengurangan risiko bencana. Daerah yang menjadi hunian suku Kaili merupakan daerah yang kerap kali mengalami bencana. Terhitung sedikitnya ada 9 bencana besar yang terjadi dalam 100 tahun terakhir yang terjadi di tanah Kaili.
Salah satu tutura mengenai mitigasi bencana adalah bangunan dan strukturnya. Bangunan dengan kearifan lokal suku Kaili merupakan hasil adaptasi dan pembelajaran dari bencana yang pernah terjadi di masa lampau. Struktur ini tercipta dari pikiran kolektif nenek moyang yang berupaya melakukan mitigasi atas bencana yang kerap terjadi.
Rumah asli suku Kaili berbahan dasar kayu untuk bangunan dan daun rumbia/sagu untuk atapnya. Bangunan rumah ini pun dibentuk menyerupai rumah panggung yang dibangun dengan jarak spesifik, seperti tinggi tanah dengan dasar bangunan dan plafon dengan lantai yang dibuat pendek untuk meringankan beban rumah. Selain itu, seluruh fondasi rumah asli Kaili berbentuk seperti fondasi pegas yang sering ditemui pada rumah-rumah di Jepang. Hal tersebut difungsikan untuk meredam getaran yang diterima saat terjadi gempa. Fondasi pun dibangun bukan dengan ditancap atau ditanam ke dalam tanah, melainkan berdasar tiga log kayu besar yang diikat kencang dan berdiri di atas batu. Oleh karena itu, alih-alih patah dan roboh seperti rumah modern dengan fondasi tanam, rumah model suku Kaili ini akan meminimalisir guncangan gempa dan mengikuti gerak tanah sehingga dapat menyelamatkan suku Kaili dari kerugian materiil dan korban jiwa.
Pengetahuan soal bangunan asli suku Kaili ini diwariskan turun-temurun. Bahkan, di Desa Sibalaya, Kabupaten Sigi ada tutura berbentuk nasihat yang berbunyi “jangan keluar rumah saat terjadi gempa”. Tutura tersebut ditujukan untuk menjadikan rumah sebagai “perahu” atau “kotak penyelamat” saat gempa terjadi. Dengan begitu, warga Kaili dapat selamat dari dampak bencana, seperti tertelan tanah atau tertimbun runtuhan bangunan karena berada di luar.
Bentuk tutura inilah yang telah menyelamatkan keluarga “tidak logis” yang telah diceritakan pada permulaan tulisan. Keluarga tersebut adalah satu dari sedikit masyarakat yang masih mengamalkan tutura dalam kehidupan sehari-hari. Saat banyak orang menilai tindakan mereka yang masuk rumah ketika gempa tidak logis, keluarga tersebut paham bahwa rumah asli Kaili dan tutura-lah yang telah menyelamatkan mereka. Saat bencana terjadi, keluarga itu hanya menaati tutura suku Kaili yang tidak masuk akal. Tindakan itulah yang sampai kapan pun akan selalu mereka syukuri.
Struktur bangunan suku Kaili seharusnya dapat menyelamatkan lebih banyak orang. Model bangunan ini juga mestinya dapat diterapkan secara umum sebagai bentuk mitigasi bencana dan perwujudan permukiman berkelanjutan sebagai poin 11 SDGs. Karakteristik wilayah yang berbeda untuk tiap daerah menghasilkan karakteristik bencana yang juga berbeda. Hal tersebut berimplikasi pada bentuk penanganan bencana yang adaptif. Tutura berupa struktur bangunan rumah suku asli Kaili semestinya dapat menjadi implementasi mitigasi bencana bagi daerah Palu dan daerah lain yang juga rawan bencana. Tutura suku Kaili sebagai kearifan lokal mestinya dapat menjadi penyelamat bagi lebih banyak jiwa pada masa yang akan datang.
Bencana Setelah Bencana
Bencana tidak selesai ketika bentala berhenti bergetar atau tanah tak lagi meluruh atau air telah menyurut. Ada banyak bencana lain yang mengintai setelah itu. Salah satunya adalah trauma psikologis. Hal inilah yang menimpa warga suku Kaili. Gangguan stres pascatrauma atau post-traumatic stress disorder (PTSD) membayang-bayangi kehidupan mereka setelah mengalami kejadian traumatis tersebut. Beberapa penyintas tidak berani untuk masuk apalagi tidur di dalam rumah sampai berminggu-minggu setelah bencana terjadi, sekalipun rumahnya utuh. Beberapa yang lain bahkan merasa was-was hanya karena berada di dekat dinding. Belum lagi perasaan duka mendalam yang dirasakan oleh mereka yang kehilangan sanak keluarga atau harta benda. Namun, bencana yang menimpa warga suku Kaili bukan hanya menimbulkan trauma individual, melainkan juga mengubah tatanan kehidupan kolektif masyarakat secara signifikan. Maka dari itu, upaya pemulihan trauma tidak cukup apabila hanya fokus pada level individual. Dibutuhkan metode pemulihan yang lebih holistik juga komunal, seperti yang dimiliki oleh suku Kaili.
Terdapat upaya pemulihan trauma berdasarkan tutura suku Kaili, yaitu tari raigo. Tarian ini dilakukan bersama-sama dengan membentuk formasi melingkar sembari melantunkan syair-syair panjang dalam bahasa yang tidak lagi digunakan dalam percakapan sehari-hari, yakni bahasa Uma Tua. Tari raigo merupakan ritus adat yang dipraktikkan pada berbagai acara atau situasi. Berbeda acara atau situasi, berbeda pula syair yang digunakan. Dalam konteks pemulihan pascabencana Palu-Sigi-Donggala, warga suku Kaili melakukan tarian ini dengan melafalkan syair yang menceritakan siklus kehidupan manusia dari lahir hingga mati dan menuturkan bagaimana kebaikan orang-orang yang telah mendahului. Makna terselubung dari syair tersebut adalah memberikan hiburan dan semangat untuk bangkit kembali, secara khusus bagi keluarga yang tengah berkabung dan secara umum bagi seluruh penyintas.
Trauma yang dialami oleh penyintas bencana lambat laun akan membekas dan berpotensi mengganggu kesehatan mental mereka. Sementara itu, kesehatan mental adalah salah satu prioritas utama untuk mencapai tujuan nomor 3 SDGs, yakni memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua. Oleh karena itu, upaya pemulihan trauma bagi penyintas bencana menjadi satu ihwal yang sangat genting. Menangani hal ini, warga suku Kaili memiliki tari raigo sebagai solusi pada proses pemulihan trauma pascabencana agar kesehatan mental seluruh penyintas stabil seperti sedia kala. Lebih dari itu, tari raigo juga menjadi sarana para warga untuk memperkuat kembali ikatan komunal yang mereka miliki dan bergerak bersama untuk bangkit kembali. Secara sederhana, tari raigo dimaksudkan untuk menyebar kebahagiaan dalam suasana duka.
Selain suasana duka yang luar biasa, lingkungan pascabencana Palu-Sigi-Donggala juga diselimuti suasana mencekam karena kriminalitas merebak di mana-mana. Secara tidak langsung, krisis membuka ruang terjadinya eskalasi kejahatan. Termasuk di Palu, Sigi, dan Donggala ketika gempa, tsunami, dan likuefaksi telah berhenti; tak sedikit masyarakat yang melakukan penjarahan dan pencurian, terutama untuk mencukupi kebutuhan pangan. Secara sederhana, kita dapat memahami bahwa tindakan tersebut terjadi karena bencana membuat mereka kekurangan atau bahkan kehilangan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu, bencana juga menyebabkan terputusnya rantai distribusi pangan ke daerah terdampak. Akibatnya, persediaan makanan habis. Oleh karena itu, tak heran jika banyak orang rela melakukan apa saja, termasuk tindakan kriminal, untuk memenuhi kebutuhan pangan belaka.
Namun, sebetulnya suku Kaili sudah memiliki siasat untuk memitigasi hal semacam itu. Istilahnya gampiri. Sebuah lumbung pangan berbentuk bangunan kecil seperti saung yang difungsikan sebagai tempat penyimpanan padi atau bahan makanan lain yang tahan lama. Gampiri ditopang oleh tiang-tiang penyangga yang dilingkari dengan kayu bundar pada bagian atasnya. Kayu bundar ini disebut tandingi. Tandingi memiliki fungsi keamanan, yakni mencegah tikus naik ke lumbung sehingga kualitas dan kuantitas bahan pangan yang disimpan di gampiri terjaga. Selain itu, gampiri tidak memiliki tangga tetap sehingga menyulitkan orang untuk mencuri.
Terdapat dua jenis gampiri, yaitu gampiri individu dan gampiri kolektif (gampiri mbaso). Gampiri individu umumnya diperuntukkan bagi ketua adat, sedangkan gampiri mbaso digunakan secara kolektif oleh warga suku Kaili untuk menyimpan hasil panen. Seyogianya, satu gampiri dapat digunakan oleh 10-15 keluarga di satu kawasan. Manfaat gampiri adalah mencegah kelaparan ketika datang krisis, seperti paceklik atau bencana. Saat bencana Palu-Sigi-Donggala terjadi, persediaan pangan yang tersimpan di gampiri dapat mencukupi kebutuhan pangan warga selama 1-2 minggu dan berhasil mengurangi risiko terjadinya penjarahan atau pencurian di kawasan yang memiliki gampiri.
Sejatinya, melestarikan gampiri merupakan upaya untuk menjaga ketahanan pangan. Ini selaras dengan salah satu tujuan SDGs, yakni menciptakan dunia tanpa kelaparan. Ketika krisis terjadi, termasuk pascabencana Palu-Sigi-Donggala, Gampiri dapat menyelamatkan banyak keluarga dengan latar belakang atau identitas apa pun dari kelaparan. Hal ini karena gampiri menjunjung tinggi nilai inklusivitas dan nondiskriminasi. Semua boleh menyimpan sesukanya, semua boleh mengambil secukupnya.
Meninggalkan Pengetahuan Lokal
Meski diakui kebermanfaatannya, gampiri sudah mulai ditinggalkan oleh warganya sendiri. Hanya sebagian kecil dari warga suku Kaili yang masih memilikinya. Karenanya, keberhasilan tradisi gampiri dalam memenuhi kebutuhan pangan warga pascabencana Palu-Sigi-Donggala tidak berskala luas. Maka dari itu, tingkat kriminalitas sangat tinggi karena kebutuhan pangan warga gagal terpenuhi. Pahitnya, bukan hanya tradisi menyimpan pangan di gampiri saja yang mulai ditinggalkan, tutura lain terkait kebencanaan pun perlahan kian mengusang. Toponimi daerah tidak lagi dihayati, larangan atau nasihat tidak lagi dipatuhi, ritus-ritus adat pun mengalami komodifikasi menjadi sekadar pentas seni.
Setidaknya terdapat dua institusi yang memicu pengabaian terhadap tutura. Pertama, hegemoni pengetahuan modern. Terdapat benturan antara pengetahuan lokal dan pengetahuan modern dalam upaya pencegahan dan penanganan bencana. Sudut pandang modernis melabeli produk-produk pengetahuan lokal sebagai takhayul. Pengetahuan lokal dinilai tidak mencapai standar ilmiah pengetahuan modern sehingga dianggap tidak rasional dan mulai ditinggalkan. Kedua, hegemoni agama. Penentangan terhadap pengetahuan lokal oleh institusi agama disampaikan melalui argumen-argumen bernuansa menghakimi, misalnya melabeli pengetahuan lokal sebagai perilaku musyrik atau mengkambinghitamkan ritus-ritus adat sebagai penyebab atas bencana yang terjadi. Terlontar pula argumen yang berbau fatalistik untuk mematahkan proses diseminasi pengetahuan lokal, misalnya anggapan bahwa bencana sepenuhnya adalah kehendak Yang Maha Kuasa dan manusia tidak dapat menghindarinya.
Dua hegemoni di atas terinternalisasi dalam bentuk stigma ‘orang aneh’ dan ‘tidak beriman’ bagi warga yang masih menerapkan tutura. Alhasil, semakin sedikit warga yang masih menghayati pengetahuan lokal. Padahal, pengetahuan lokal merupakan bagian integral dari jati diri masyarakat. Meninggalkan pengetahuan lokal berarti meninggalkan jati diri.
Kembali pada Pengetahuan Lokal
Tak hanya persoalan jati diri, tutura juga berkontribusi terhadap tercapainya beberapa visi dalam SDGs. Misalnya, salah satu tujuan turunan dari SDGs poin ke-11–mewujudkan permukiman yang inklusif, aman, nyaman, dan berkelanjutan–adalah mengurangi risiko bencana. Warga suku Kaili memiliki tutura mengenai struktur bangunan dan toponimi daerah sebagai jawabannya.
Tutura juga tidak luput dalam mewartakan langkah-langkah untuk mengatasi krisis yang terjadi akibat bencana, seperti kelaparan serta trauma psikososial. Tradisi menyimpan pangan di gampiri dan tari raigo adalah dua amanat dari tutura yang dapat dijadikan juru selamat guna mengatasi krisis tersebut. Krisis pascabencana perlu diatasi segera karena apabila berkepanjangan akan menghambat upaya untuk mencapai tujuan-tujuan lain dari SDGs. Misalnya, menghapus kelaparan pada poin ke-2 dan memastikan kehidupan yang sehat serta sejahtera baik dari segi mental maupun fisik pada poin ke-3.
Tutura yang tersiar di suku Kaili, Sulawesi Tengah hanyalah satu dari sekian banyak produk pengetahuan lokal yang berguna dalam pencegahan dan penanganan bencana di seluruh Indonesia. Mengapa hampir setiap daerah memiliki pengetahuan lokal terkait kebencanaan masing-masing yang sifatnya spesifik dan unik? Karena karakteristik bencana di setiap daerah berbeda-beda dan pengetahuan lokal adalah pintu masuk terbaik untuk memahami hal tersebut. Dengan memahami karakteristik bencana secara detail dan holistik, maka upaya pencegahan dan penanganannya dapat lebih berkelanjutan, efektif, tepat sasaran, dan berpotensi menyelamatkan lebih banyak orang.
Akan tetapi, kembali menghayati, memaknai, dan mengamalkan pengetahuan lokal bukan perkara mudah. Hegemoni pengetahuan modern dan agama menjadi tantangan tersendiri. Diperlukan siasat khusus dan serius untuk mengupayakan hal tersebut. Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah “mengilmiahkan” atau “melogiskan” pengetahuan lokal itu sendiri. “Mengilmiahkan” atau “melogiskan” diartikan sebagai pemaknaan kembali pengetahuan lokal dengan justifikasi ilmiah yang bersandar pada pengetahuan modern. Dengan begitu, pesan-pesan yang tersirat dalam pengetahuan lokal dapat lebih diterima untuk kemudian diberlakukan oleh masyarakat.
Pada akhirnya, sinergi antara pengetahuan lokal dan pengetahuan modern menjadi sangat penting dalam konteks kebencanaan. Pengetahuan lokal dapat memberikan gambaran yang paling akurat mengenai karakteristik, pola, sampai cara pencegahan dan penanganan bencana. Di saat yang sama, tabiat manusia modern selalu memerlukan pembenaran rasional yang berbasis pada bukti-bukti ilmiah sebelum memercayai atau melakukan sesuatu. Maka dari itu, perkawinan pengetahuan lokal dengan pengetahuan modern merupakan hal yang krusial. Keduanya tidak perlu saling melawan apalagi saling menghapuskan.
Penulis : Afiyati Din Khailany
Juara 1 Kategori Mahasiswa