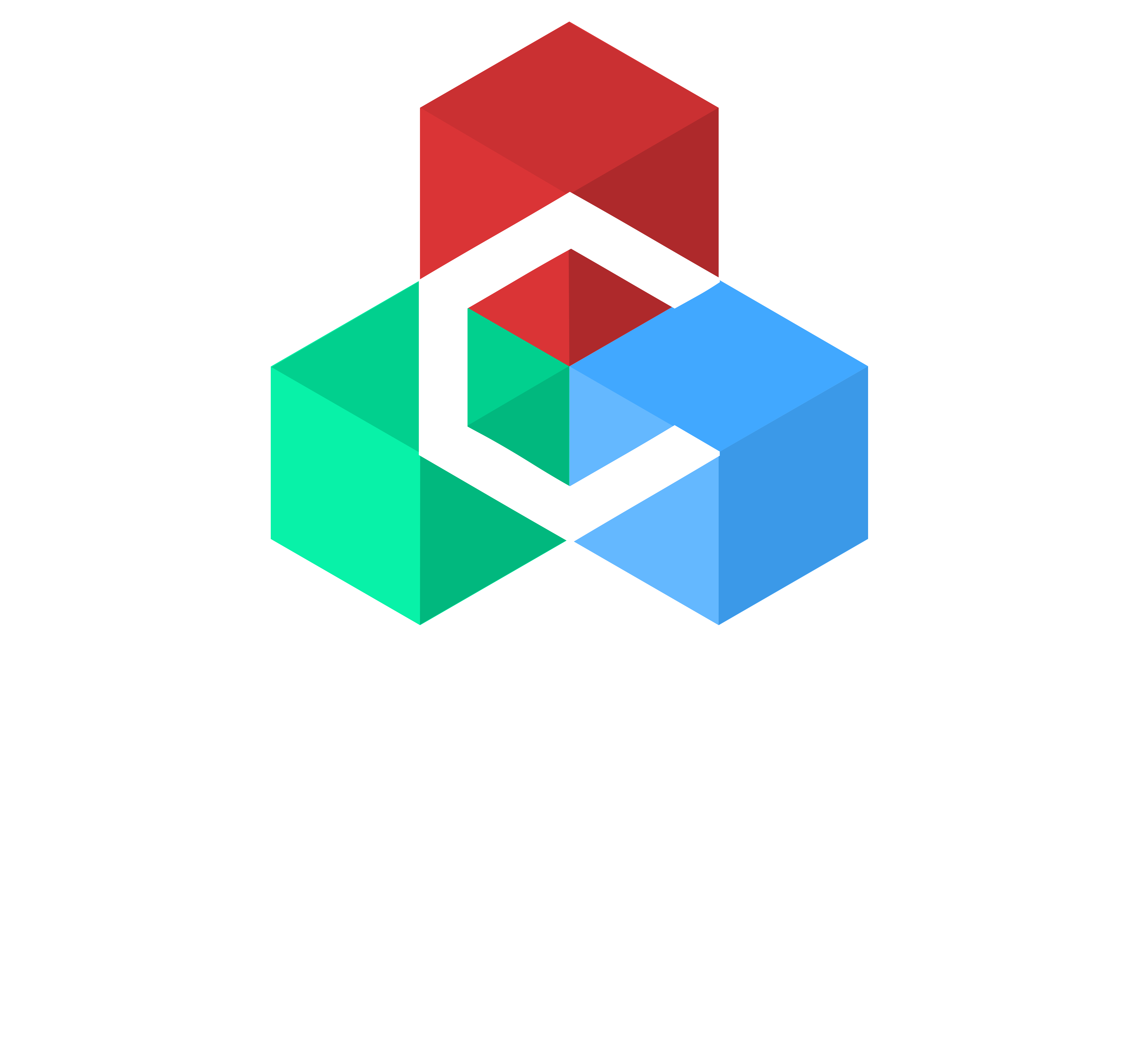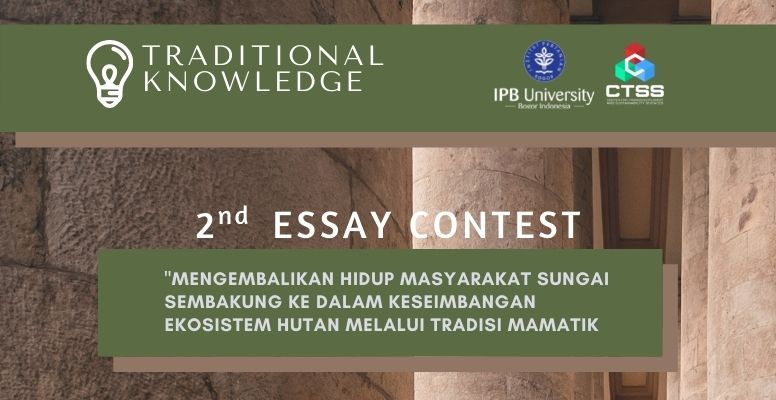1. PENDAHULUAN
Kehidupan masyarakat Sungai Sembakung sangat terpaut erat dengan ekosistem hutan. Komunitas adat yang mendiami wilayah pedalaman hutan di Kalimantan Utara ini mengandalkan beragam hasil hutan tidak hanya sebatas pemenuhan kebutuhan ekonomi akan tetapi juga ritus budaya. Keberadaan hasil hutan pada ritus budaya yang berlangsung siklik daur hidup menjadi objek sakral.
Aktivitas keseharian tidak lepas dari sungai sebagai lintasan penghubung kehidupan penduduk dengan negara tetangga. Hamparan hutan hujan tropis atau dikenal sebagai hutan primer menjadi ekosistem yang begitu esensial. Keberadaanya merupakan jantung kehidupan bagi seluruh makhluk yang hidup di bumi. Pepohonan tumbuh di dalam hutan primer menjadi penghasil oksigen, sehingga menjadi penyangga bagi kehidupan seluruh makhluk hidup di planet ini.
Akan tetapi, mirisnya, seiring perkembangan dan dinamika zaman, keberadaan hutan hujan tropis mulai terancam oleh aktivitas manusia yang bersifat eksploitatif. Dalam kurun waktu satu dekade, Rhett A. Butler dari situs berita lingkungan Mongabay (2020) melaporkan bahwa daerah tropis mengalami kehilangan hutan primernya secara eksponensial. Dalam artikel tersebut, dikatakan bahwa sejak tahun 2002, bagian wilayah tropis di planet bumi ini telah kehilangan lebih dari 60 juta hektar hutan primer atau seukuran dengan 1,3 kalinya Pulau Sumatera. Apabila kegiatan ekspolitasi hutan hujan tropis masih terus berlangsung, bukan tidak mungkin hutan hujan tropis akan punah, begitu juga seluruh makluknya hidup yang menghuni, termasuk manusia.
Sayangnya, sering perkembangan zaman, aktivitas manusia semakin intensif mengolah sumber daya alam, hingga sering kali mengabaikan dampak keseimbangan alam. Aktivitas yang dilakukan manusia dalam kegiatannya untuk bertahan hidup semakin mengarah kepada perilaku konsumtif yang membahayakan kehidupan makhluk di muka bumi. Dikenal dengan istilah Antroposen, aktivitas manusia yang sering kali bersifat merusak keseimbangan ekosistem ini, berdampak luar biasa, hingga membawa pengaruh global.
Seiring dinamika perubahan dan perkembangan zaman dan perilaku Antroposen manusia yang menjadi-jadi membuat ekosistem hutan mengalami ancaman kerusakan akibat eksploitasi. Keanekaragaman makhluk yang menghuni ekosistem hutan primer atau dikenal sebagai hujan tropis diambang bahaya kepunahan.
Persoalan yang diuraikan dalam essay ini mengambil posisi kontra terhadap perspektif Malthusian sebagai penyebab kerusakan sumber daya alam kehutanan. Perspektif Malthusian beranggapan bahwa kerusakan lingkungan disebabkan karena banyaknya populasi manusia yang melebihi kapasitas sumber daya alam. Perspektif Malthusian ini tidak berlaku di daerah aliran Sungai Sembakung, perbatasan dengan Sabah Malaysia yang memiliki populasi penduduk tidak banyak akan tetapi masih terdampak kerusakan lingkungan akibat penetrasi kapital. Karena itu, penulis menyetujui pendekatan ekologi politik yang menilai bahwa bukan banyaknya populasi penduduk penyebab kerusakan lingkungan melainkan sistem kapitalisme yang didorong oleh praktik konsumsi dari penduduk. Adanya penetrasi kapital yang kuat mendorong manusia untuk melakukan kegiatan konsumsi yang saling berkait antar satu wilayah dengan lainnya.
Dalam ukuran pembangunan, pertumbuhan ekonomi (economic growth) merupakan indikator utama yang selalu diupayakan negara karena dianggap berkorelasi dengan kesejahteraan penduduknya, baik oleh Indonesia maupun Malaysia. Economic growth merupakan skema dari sistem kapitalisme dunia. Sementara itu, jantung dari kapitalisme itu sendiri adalah consumption yang sering kali tidak memandang apakah penting dan tidaknya konsumsi tersebut bagi penduduk setempat. Seperti yang terjadi pada kawasan ini, keberadaan korporasi tanaman karet dan kelapa sawit di hulu Malaysia yang sebenarnya menyediakan “supplay” kebutuhan industri global. Masyarakat dalam golongan kelas terbawah akan menjadi buruh yang bekerja dengan upah tidak seberapa pada korporasi tersebut.
2. ISI
Dua desa dipelosok Provinsi Kalimantan Utara menyimpan kekayaan budaya tersembunyi. Berlokasi di wilayah administratif Kabupaten Nunukan, Kecamatan Sembakung, desa Atap dan desa Tanjung Langsat dikenal sebagai tempat bermukimnya sekumpulan ibu-ibu yang masih mewarisi keterampilan seni anyaman rotan mamatik. Memanfaatkan tumbuhan endemik rotan yang didapatkan tidak jauh dari lokasi pemukiman, material budaya mamatik tidak hanya menampilkan keindahan motif anyaman tapi juga cerita leluhur yang melatarbelakangi pembuatannya penuh dengan makna.
Sinumandak dan agigimpong adalah motif yang paling dikenal oleh masyarakat karena menceritakan kisah aliansi kelompok melalui perkawinan yang tidak selalu disetujui oleh perempuan sendiri sebagai individu yang dijodohkan. Motif keduanya tidak hanya menampilkan desain estetis yang memperindah material budaya anyaman rotan mamatik, tapi juga simbol perlawanan kaum perempuan terhadap siklus aliansi adat yang bersifat patriarkis. Perempuan bisa menjadi pejuang atas kesewenang-wenangan praktik adat dan juga beragam praktik dinamika perubahan lingkungan.

Gambar 1. Seorang perempuan penganyam mamatik sedang mengajarkan pendatang
(dokumentasi penulis)
Tikar mamatik telah menjadi material budaya yang esensial bagi keberlangsungan ritus adat masyarakat Sungai Sembakung, terutama pada tradisi perkawinan. Tikar menjadi benda pertukaran, sebagaimana tradisi masyarakat arkais yang dijelaskan dalam The Gift (Mauss: 1954) dari klan keluarga perempuan atas “pulut” (maskawin) yang diberikan klan keluarga lelaki. Anyaman tikar mamatik diartikan sebagai bekal yang diberikan oleh sang ibu kepada anak perempuannya untuk menjalani hidup di lingkungan baru, klan keluarga suaminya. Keberlangsungan pernikahan menjadi terhambat apabila tidak ada tikar mamatik sebagai benda yang dibawa oleh si perempuan kepada klan keluarga laki-laki.
Akan tetapi, perubahan pengelolaan sumber daya yang dewasa ini terjadi mengarah pada eksploitasi hutan membuat keberlangsungan tradisi mamatik menjadi terancam. Kondisi demikian secara langsung berimbas pada potensi distorsi tatanan sosial yang selama ini dijalankan oleh masyarakat. Eksploitasi pengelolaan lahan hutan membuat masyarakat terperangkap dalam kepungan korporasi perkebunan sawit. Hal tersebut membawa dampak pada musnahnya keanekaragaman hayati hutan, termasuk keberadaan pohon rotan. Pepohonan lainnya yang biasa menjadi bagian dari penjaga agar area tangkapan sungai Sembakung dibabat habis berganti menjadi monokultur perkebunan sawit. Kondisi demikian menjadi salah satu penyebab area hilir Sungai Sembakung tidak mampu menampung debit air dalam jumlah yang tinggi ketika musim penghujan sehingga mengakibatkan banjir.
Bencana hidrolik banjir dialami oleh komunitas di hilir Sungai Sembakung hampir setiap tahunnya. Tidak seperti banyak kasus bencana banjir yang lazimnya menimpa penduduk dibantaran sungai, aliran yang menembus batas negara, yakni hulu sungai yang berada di wilayah Sabah, menjadikan kasus bencana yang dialami oleh masyarakat menjadi berbeda. Meski asumsi beredar bahwa pengelolaan sumber daya hutan oleh pihak negara Malaysia secara tidak bertanggung jawab sehingga menyebabkan bencana banjir yang terjadi, akan tetapi belum ada penyelesaian secara bilateral mengenai persoalan ini (Hastuti, 2020).
Kebijakan pengelolaan yang berbeda antara hulu dan hilir berdampak pada kondisi tidak menguntungkan pada satu pihak, dalam kasus Sungai Sembakung adalah wilayah Indonesia. Perkampungan hilir yang lokasinya masuk wilayah kecamatan Lumbis dan kecamatan Sembakung, Kalimantan Utara, Indonesia, menjadi terdampak dari pengelolaan sumber daya hutan secara tidak bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat di wilayah hulu yang terletak di sekitar Sungai Pensiangan dan Sungai Sapulut, Sabah Malaysia.
Desa Atap dan Desa Tanjung Langsat menjadi bagian dari area hilir Sembakung yang terdampak banjir. Tidak hanya mengakibatkan bencana yang sifatnya ekologis, perubahan pengelolaan hutan dibawah korporasi perkebunan sawit menimbulkan distorsi sosial pada masyarakat. Ibu-ibu banyak menghabiskan waktu sebagai buruh di perkebunan kelapa sawit dengan gaji yang tidak seberapa. Sementara kegiatan “mamatik” mulai ditinggalkan, dan tidak sempat lagi terjadi transmisi pewarisan keterampilan menganyam. Padahal, anyaman mamatik asal dua desa ini telah menembus pasar ekspor Eropa dan beberapa kali ditampilkan dalam perhelatan pameran budaya di luar negeri.
Mengacu pada theory of access (Ribot & Peluso, 2003), penduduk Desa Atap dan Desa Tanjung Langsat tidak memiliki “bundle of power” atas kepemilikan terhadap “property” lahan. Korporasi sawit telah mengekslusi masyarakat melalui relasi kuasa tidak setara yang dilanggengkan oleh praktik neo-liberal atas dukungan negara. Akibat bagi komunitas berbasis DAS tidak hanya memengaruhi ekslusi penduduk di sekitar areal lahan, tapi juga semakin memperparah banjir pada perkampungan di wilayah yang lokasinya lebih hilir.
Namun demikian, bagi para ahli ekologi politik, peristiwa akumulasi kapital yang berdampak pada kerusakan ekosistem lingkungan pada saat bersamaan justru mendorong “environmental movements”—political ecologist contributed to the creation of general theories suggesting that capital accumulation necessarily undermines the system upon which it depends, for example, propelling environmental movement (O’Connor dalam Robbins 2012: 84). Kesadaran mengenai “environmental justice” ikut disuarakan oleh penggiat lingkungan secara mengglobal. Dalam prosesnya, kesadaran mengenai pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan menumbuhkan, tidak hanya membangun kesadaran “environmental justice” akan tetapi membangun kerangka environmentality (Agrawal, 2005) pada komunitas yang relung hidupnya terancam. Bahkan pada kodisi ekosistem yang mengancam keberlangsungan hidupnya, manusia sebagai makhluk individu maupun dalam komunitas bisa menjadi seorang environmentalist, hidup dengan ideologi untuk melestarikan dan memperbaiki lingkungannya.
Satu hal yang tidak bisa dilepaskan dari kerangka “Environmentality” komunitas adalah feminisme lingkungan yang mengilhami gerakan akar rumput mengenai “environmental movement”. Feminisme lingkungan menjadi pintu masuk untuk melihat persoalan yang selama ini luput dari perhatian masyarakat terbelenggu oleh budaya patriarki. Padahal, perempuan merupakan kelas sosial yang selama ini dipinggirkan baik dalam skema sosial budaya, politik maupun ekonomi memiliki potensi sebagai environmentalist. Potensi perempuan sebagai penjaga kesinambungan ekosistem alam dan kehidupan sosial budaya dari manusia-manusia di perbatasan tidak bisa dipandang sebelah mata.
Bencana banjir yang dialami oleh penduduk saling terpaut antara wilayah hulu dan hilir dipengaruhi oleh berbagai diskursus ekologi politik seperti penetrasi korporasi, peraturan pengelolaan sumber daya hutan oleh pemerintah, juga melibatkan pandangan masyarakat mengenai pemanfaatan lingkungan. Perubahan lingkungan dan bencana yang dialami menciptakan ruang kesadaran mengenai bagaimana pengelolaan sumber daya alam dikatakan ideal bagi masyarakat. Proses penyadaran mengenai pengelolaan sumber daya alam yang sesuai dengan daya dukung ekosistem lingkungan dan kebutuhan sosial, ekonomi dan budaya dari masyarakat merupakan aspek yang mengarah pada gagasan “environmentality” komunitas perbatasan.
Satu hal yang menarik terjadi justru di wilayah perkampungan hilir, area tersebut sebenarnya mengalami dampak banjir serta kerusakan hutan akibat eksploitasi korporasi. Terpapar atas kondisi demikian membuat masyarakat mulai menyadari terhadap dampak kerusakan akibat pengelolaan hutan yang tidak mempertimbangkan daya dukung dan keanekaragaman hayati dari ekosistem hutan dan sungai. Kondisi tersebut menjadi pemantik bagi pengembangan kelompok pengrajin kriya rotan mamatik yang diinisiasi oleh seorang seniman Kriya yang berasal dari Swiss yakni Margrit Linder (margritlinder.ch, 2015). Dapat dikatakan Margrit Linder adalah seorang environmentalist yang berkreasi menciptakan karya seni perhiasan berbahan dasar bukan emas. Ia mengkreasikan bebatuan dan material yang berasal dari tumbuhan untuk dikreasikan dalam bentuk perhiasan. Bersama suaminya yang seorang antropolog, Margrit dibantu suaminya Adrian Linder melakukan pemberdayaan terhadap budaya kriya yang dimiliki oleh perempuan di sepanjang Sungai Sembakung.

Gambar 2. Tikar/Kriya Anyaman Mamatik
(dokumentasi: http://margritlinder.ch )
Pengkondisian program pemberdayaan yang dilakukan oleh Margrit Linder dapat dikategorikan sebagai proses “environmentality” dari masyarakat yang berada di hilir. Proses inisiasi pengetahuan mengenai pelestarian lingkungan justru dilakukan oleh penduduk dari luar “Nation-State” Indonesia namun memiliki kesadaran menglobal terhadap environmental justice pada perempuan dan lingkungan. Apabila kembali lagi pada persoalan awal, sesungguhnya perusakan hutan dan penyebab banjir bukan persolan “Nation-State” yang berlainan, akan tetapi praktik konsumsi dan penetrasi kapital.

Gambar 3. Perempuan sedang menganyam kriya mamatik
(dokumentasi: http://margritlinder.ch )
Dalam kerangka praktik “environmentality” telah disampaikan oleh Agrawal (2005: 166) bahwa “environmentality” here to denote framework of understanding in which technologies of self and power are involved in the creation of new subjects concerned about the environment. Dari pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa masyarakat setempat, khususnya perempuan menjadi subjek yang mengidentifikasi praktik perusakan lingkungan dan kembali mempelajari pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan oleh leluhur. Pada prosesnya, masyarakat menyadari, praktik yang diwariskan oleh leluhur melalui kreasi budaya material mamatik dianggap lebih dapat menciptakan pengelolaan sumber daya alam yang sesuai dengan daya dukung ekosistem lingkungan.

Gambar 4. Perempuan sedang menaiki perahu untuk mengambil rotan sebagai bahan baku anyaman mamatik
(dokumentasi: http://margritlinder.ch)
Awalnya, masyarakat mulai meninggalkan kegiatan menganyam mamatik karena penduduk perempuan selain disibukkan dengan kegiatan berladang, terlibat menjadi pekerja buruh di perkebunan sawit. Hal tersebut dilakukan akibat kebutuhan untuk membantu peran suami dalam pemenuhan ekonomi keluarga. Margrit mulai melakukan internalisasi nilai mengenai bahaya pengalihfungsian areal hutan menjadi lahan menjadi sawit salah satunya adalah bencana banjir yang tiap tahunnya melanda perkampungan warga.
Melalui komodifikasi mamatik hingga melampaui kualifikasi sebagai barang ekspor bertujuan agar perempuan memiliki opsi pendapatan yang tidak mendistorsi budaya. Perempuan masih dapat berkreasi melalui mamatik, mendapatkan uang, mengurus rumah dan merawat anak, serta menjaga ekosistem dengan menumbuhkembangkan kriya yang dibuat secara tradisional. Pekerjaan ini dilakukan oleh perempuan yang dalam pengembangannya dibantu oleh seorang seniman Kriya yang berasal dari Swiss, yakni Margrit Linder. Meski dalam pengembangannya Margrit menghadapi kesulitan untuk mengisi kontainer pasokan karya mamatik yang akan diekspor.
 Gambar 5. Showcase kerajinan kriya mamatik yang telah diproduksi
Gambar 5. Showcase kerajinan kriya mamatik yang telah diproduksi
(dokumentasi: http://margritlinder.ch)
Dengan demikian, proses untuk menjadi “environmentalist” belum atau tidak akan pernah final bagi masyarakat di perbatasan. Prosesnya menjadi sangat fluktuatif, tergantung bagiamana ekosistem ekologi politik dapat menciptakan arena kondusif bagi penumbuhan kesadaran ini. Untuk itu, peran perempuan dalam keberlangsungan ekosistem komunitas aliran Sungai Sebakung dapat menjadi fondasi kokoh bagi pemantik gerakan “environmentality”. Apabila dikaitkan dengan tulisan Rocheleau, dkk (2006) yang menguraikan bagaimana akar perspektif feminisme ikut berkontribusi dalam kajian mengenai isu-isu lingkungan, komunitas perempuan “mamatik” bergerak pada poros perjuangan serupa.
Melalui kriya anyaman “mamatik”, sesungguhnya perempuan-perempuan penduduk setempat sedang menyuarakan kritik feminisme atas pandangan bahwa relasi manusia dan lingkungannya yang hanya dipengaruhi oleh struktur ekonomi dan politik global. Dalam relasi tersebut, yang terjadi adalah justru pengabaian adanya unsur gender sebagai implikasi hubungan tersebut yang sering kali menjadi komunitas terpinggirkan. Dalam konteks ini menarik untuk memperhatikan pemikiran dari Rocheleau dkk (Rocheleau, dkk 2006: 28), bahwa diferensiasi gender tidak bisa dilepaskan dari komunitas lokal yang berpengaruh pada agenda politik global:
“Feminist political ecology treats gender as a critical variable in shaping resource access and control, interacting with class, caste, race, culture, and ethnicity to shape processes of ecological change, the struggle of men and women to sustain ecologically viable livelihoods, and the prospects of any community for “sustainable development….“The analytical framework presented here brings a feminist perspective to political ecology. It seeks to understand and interpret local experience in the context of global processes of environmental and economic change.”
Dalam pergulatan perjuangan politik elit lokal, penulis melihat adanya pengabaian terhadap perempuan. Hampir tidak pernah perempuan yang bekerja sebagai ibu rumah tangga dilibatkan dalam diskusi mengenai pengambilan kebijakan pengelolaan lingkungan di tingkat desa, ataupun dalam tingkatan yang lebih tinggi. Padahal, perempuan menempati posisi penting bagi perjuangan aktivisme pelestarian lingkungan pada ranah akar rumput dan penyelesaian persoalan banjir di hulu dapat mereplikasi apa yang telah dilakukan pada wilayah hilir. Untuk itu, pengelolaan daerah aliran sungai yang melibatkan dua negara melalui serangkaian kesepakatan bilateral perlu didasari atas kebutuhan masyarakat pada ranah yang paling kecil yakni rumah tangga (household).
3. PENUTUP
Dalam mengkaji persoalan lingkungan masyarakat berbasis hutan tidak dapat dilepaskan dari kompleksitas persoalan relasi kekuasaan dan politik, yang ada di tingkat lokal, nasional, regional, maupun global. Oleh karena itu, menjadi penting dalam penelusuran persoalan lingkungan untuk mencari hal apa saja yang terjadi di lokal, sebagai dampak dari relasinya dengan tingkatan regional maupun global. Sebagaimana skema perubahan lanskap sistem ekologi yang digambarkan oleh Robbins (2012), yang menyuguhkan alur perubahan lanskap ekologi. Terlihat alur dalam skema tersebut dipengaruhi oleh apa yang terjadi pada level transnasional, negara, yang memengaruhi komunitas untuk kemudian sampai pada perilaku konsumtif, dan akhirnya berimbas pada lanskap ekologi dan alurnya kembali lagi skema transnasional.
Dalam esai ini, penulis mencoba berangkat dari permasalahan yang terjadi dalam konteks lokal, yakni bencana banjir di perbatasan negara. Akan tetapi dalam kerangka kebijakan pengelolaan lingkungan, dampak bencara hidrometrologi yang terjadi di perbatasan berkaitan dengan hubungan transnasional (bilateral) Indonesia-Malaysia. Penyelesaian persoalan bencana banjir di perbatasan masih terhambat kesalahan cara pandangan masyarakat, elit lokal, dan negara mengenai pengelolaan lingkungan yang berfokus pada “alih menyejahterakan manusia” dengan memposisikan ekosistem alam sebagai prioritas yang berada dibawahnya.
Apakah musti melanggengkan cara pandang Antroposen yang selalu memposiskan manusia sebagai kasta tertinggi dalam rantai ekosistem kehidupan di muka bumi? Cara pandang “environmentality” bagi penulis dapat menjadi gerbang awal mengikis kultur eksploitatif yang dihasilkan oleh masyarakat pada era kapitalisme seperti sekarang. Akan tetapi menurut hemat penulis, “environmentality” belum dapat sepenuhnya merombak kultur eksploitatif Antroposen. Pada kelanjutannya, “environmentality” perlu didukung oleh cara pandang teoritis yang tidak lagi menempatkan alam sebagai kelas kedua, melainkan setara dengan manusia.
Berkaitan dengan problema Antroposen yang menyoal ketimpangan kuasa antara relasi manusia dengan makhluk lainnya di muka bumi, menarik untuk gagasan “embedded” dari Tim Ingold (2000). Gagasan “embedded” membawa kita menelisik kemelekatan manusia dengan alam dan budayanya melalui hubungan korespondensi. Hal demikian dapat menjadi cara pandang baru dalam mengkaji hubungan manusia dan organisme lainnya yang sama-sama menghuni ekosistem DAS dan bumi secara lebih luas. Karena itu, dengan melestarikan tradisi kriya mamatik, tidak hanya menjadi upaya menyeimbangkan kembali ekosistem hutan yang selama ini terganggu aktivitas eksploitatif manusia akan tetapi juga menempatkan tumbuhan rotan sebagai material adat utama dan sifatnya esensial dalam penentu berjalannya siklus ritus daur hidup masyarakat di Sungai Sembakung.
Penulis : Puji Hastuti
Juara 1 Kategori Pascasarjana