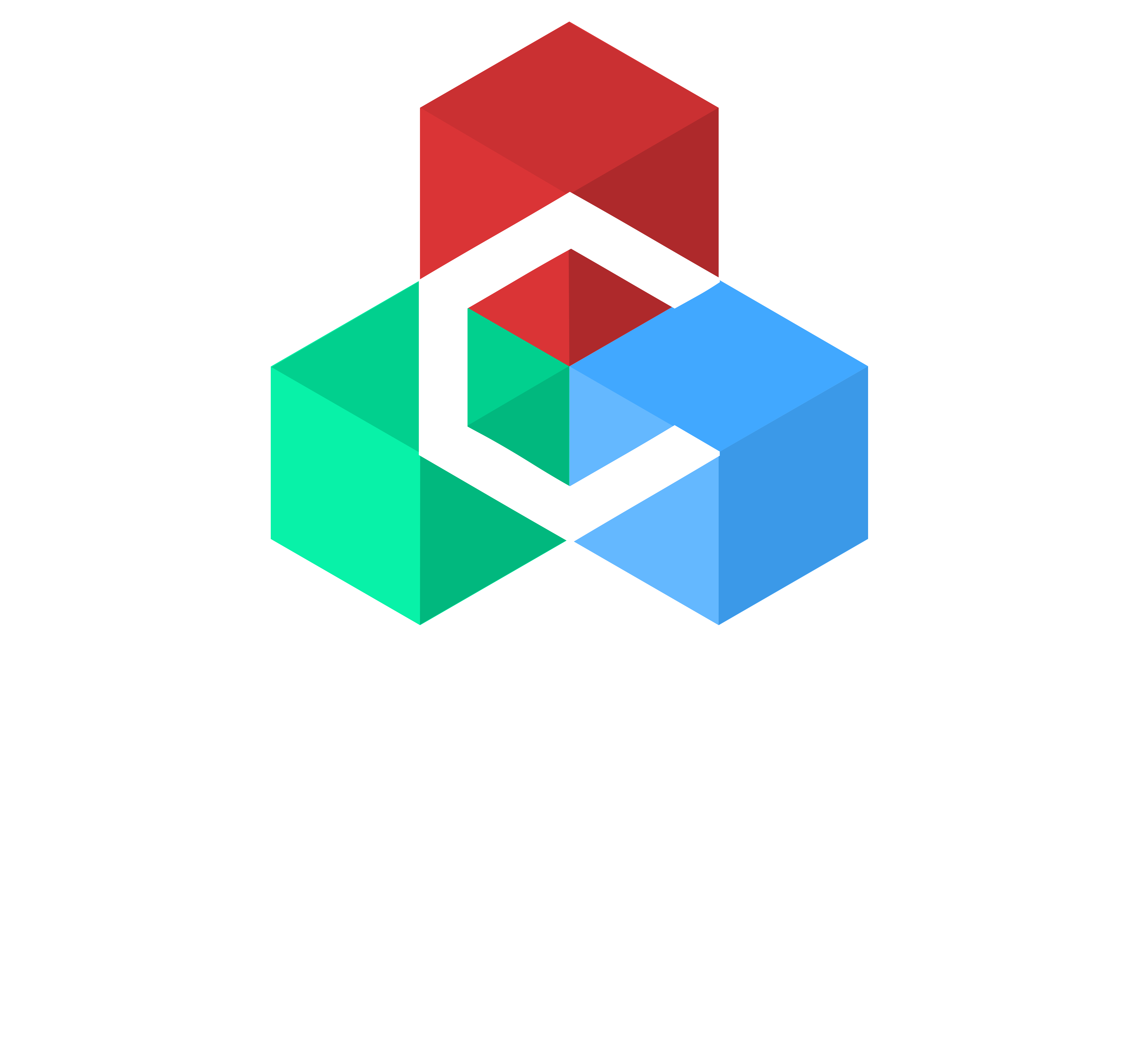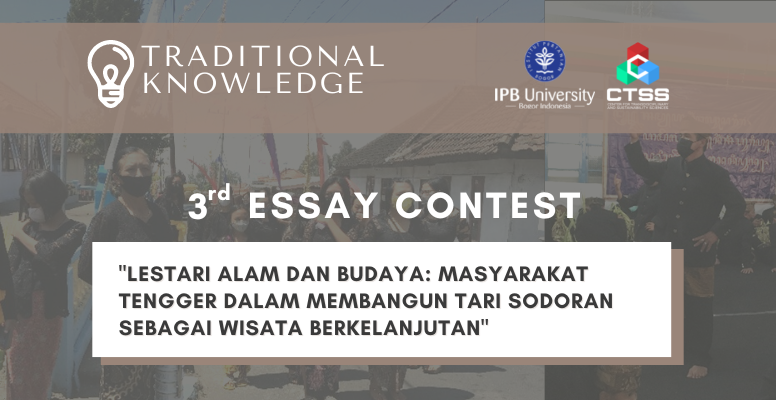Pesona alam Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) tentu tidak asing di telinga kita. Kawasan pariwisata tersebut menyuguhkan pemandangan kaldera Gunung Bromo yang eksotis. Wisatawan kerap dibuat terpukau dengan kawah Gunung Bromo, jajaran bukit Teletabis, maupun lautan pasir yang membentang sepanjang mata memandang. Banyaknya wisatawan yang berkunjung di destinasi pariwisata unggulan Indonesia ini turut menyumbangkan devisa negara dalam jumlah yang besar.
Menanggapi antusiasme wisatawan, banyak hotel-hotel yang dibangun oleh investor di sekitar wilayah taman nasional tersebut. Mereka pun menjadi pilihan tempat singgah para wisatawan. Di sisi lain, masyarakat Tengger pun turut mengambil peluang ekonomi dalam wisata TNBTS. Namun, sangat disayangkan karena peran mereka dalam sektor pariwisata masih terbatas, seperti menjadi sopir jeep, ojek, penyedia tunggangan kuda, maupun menjadi pelayan di hotel. Padahal sebagai suku yang mendiami kawasan Gunung Bromo, masyarakat Tengger seharusnya menjadi aktor yang dominan dalam pengelolaan pariwisata. Kondisi kurang menguntungkan ini muncul karena pengembangan pariwisata biasanya masih bersifat top down di mana pemerintah belum melibatkan berbagai lapisan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan pariwisata.
Masyarakat Tengger seharusnya punya otoritas besar dalam mengelola sumber daya mereka. Pengembangan pariwisata yang bersifat bottom up menjadi alternatif pilihan guna menjadikan masyarakat Tengger sebagai aktor yang aktif mengeksplorasi kekayaan alam dan budaya di sekitar mereka. Sistem bottom up dapat menempatkan mereka dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengembangan pariwisata hingga mewujudkan masyarakat Tengger yang berdaya dan adaptif.
Perlu digarisbawahi bahwa sekalipun TNBTS mampu mendatangkan banyak keuntungan, masyarakat Tengger tidak dapat sepenuhnya bergantung pada TNBTS. Hal ini bisa dilihat dari kebijakan pemerintah beberapa waktu lalu dalam menutup kawasan wisata tersebut sebagai dampak Covid-19. Sebagian masyarakat pun kehilangan sumber pendapatan utama mereka dan kembali beralih ke ladang. Mengatasi kondisi yang tidak tentu ini, baik masyarakat Tengger maupun pemerintah dapat bekerja sama menciptakan wisata alternatif berkelanjutan. Tentu ini sekaligus menjadi upaya untuk meminimalisasi eksploitasi alam.
Lagi pula terdapat satu pemahaman tentang TNBTS sebagai kawasan konservasi yang perlu diluruskan. Konsep taman nasional atau konservasi ialah untuk mengeliminasi aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah konservasi tersebut. Taman nasional memang dapat dimanfaatkan untuk sarana rekreasi maupun area untuk edukasi kultural. Mirisnya beberapa tahun terakhir ini, tepatnya di tengah lautan pasir ditemukan bangunan ruko bersemen yang berjajar menjajakan makanan maupun cenderamata khas Tengger. Tentu saja situasi ini mengingkari batas-batas yang digariskan dalam konsep konservasi.
Seperti yang penulis singgung sebelumnya, masyarakat Tengger dapat mengeksplorasi kearifan lokal dan membentuknya sebagai wisata berkelanjutan. Sudah waktunya bagi masyarakat Tengger dan pemerintah beranjak dari bentuk wisata massal atau sebuah wisata yang dikonsumsi oleh berbondong-bondong wisatawan dan rentan dengan eksploitasi. Dalam wisata massal biasanya wisatawan datang hanya untuk memanjakan mata dan pulang dengan mengantongi foto-foto estetik semata. Lantas, bagaimana dengan tawaran suguhan wisata berkelanjutan yang unik? Wisata yang terkesan eksklusif, bukan karena perlu merogoh kocek yang dalam, namun karena mampu mentransfer nilai budaya, mengedukasi, dan menciptakan pengalaman yang berkesan. Model wisata ini bisa ditumbuhkan melalui kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat Tengger. Lantas, kearifan lokal seperti apa yang berpotensi menjadi wajah baru pariwisata masyarakat Tengger? Serta bagaimana strategi yang dapat mereka implementasikan guna mengembangkan pariwisata tersebut? Dua pertanyaan penting ini lah yang menjadi fokus dalam pembahasan selanjutnya.
Penulis akan menguraikan jawaban atas pertanyaan di atas dengan memaparkan gambaran masyarakat Tengger terlebih dahulu. Masyarakat Tengger sebenarnya tersebar dalam empat kabupaten, yaitu Malang, Lumajang, Pasuruan, dan Probolinggo. Mayoritas masyarakat bermata pencaharian dengan berladang dan bergerak di sektor pariwisata seperti yang penulis sebutkan sebelumnya. Masyarakat Tengger yang memeluk agama Hindu ini masih melestarikan adat mereka. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka sangat dekat dan terus terhubung dengan alam, leluhur, dan kerabatnya. Sebagai wujud syukur mereka atas berkah alam dari Sang Hyang Widi Wasa, maka mereka secara rutin melaksanakan ritual adat.
Ritual adat bagi masyarakat Tengger menjadi hal yang tidak bisa ditawar. Dalam kondisi apapun, mereka tetap melaksanakan ritual adat sesuai dengan waktu yang disepakati. Ada berbagai ritual yang diselenggarakan oleh masyarakat Tengger, di antaranya ritual Kasada, Unan-Unan dan Karo. Tentunya setiap ritual memiliki pemaknaan yang berbeda-beda. Dalam ritual Karo yang memperingati kelahiran manusia biasanya terdapat tari Sodoran. Tarian ini menjadi salah satu tarian khas masyarakat Tengger yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Gambar 1. Kepala desa Ngadisari, Jetak, dan Wonotoro beserta dukun membuka acara
(Dokumentasi penulis)
Secara spesifik penulis akan mendeskripsikan tari Sodoran yang diselenggarakan oleh masyarakat Tengger yang tinggal di Probolinggo. Uniknya, tari Sodoran di sana melibatkan tiga desa sekaligus yang meliputi Desa Ngadisari, Desa Jetak, dan Desa Wonotoro. Ada tiga peran yang dipertukarkan secara bergantian oleh ketiganya, yaitu sebagai tuan rumah, wali, dan besan.
Penulis turut serta dalam rangkaian tari Sodoran pada Agustus 2021 lalu di mana Desa Wonotoro berperan sebagai tuan rumah. Mulanya laki-laki yang terlebih dahulu berkumpul di aula desa dengan mengenakan pakaian adat berupa udeng, jas hitam, dan jarik sebagai bawahan. Mereka pun duduk berbanjar dengan rapi dan menyisakan ruang di tengah sebagai tempat untuk menari. Peralatan Sodoran yang telah disucikan disebut dengan jimat kelontongan yang terdiri dari empat buah tombak bambu atau sodor dan sebuah tanduk kerbau. Setelah dibacakan mantra mekakat atau pembuka oleh Pak Dukun, tari Sodoran pun dimulai dari satu orang lalu bertambah menjadi dua, hingga empat orang secara bergantian. Puncaknya ialah ketika kepala desa yang menjadi wali dan besan ikut menari dan saling bebesanan. Berdasarkan hasil wawancara dengan sesepuh desa, yaitu Pak Sawi (nama samaran), penambahan jumlah tersebut merepresentasikan upaya makhluk hidup, terutama manusia, untuk bertumbuh dan merajut pertalian kekerabatan. Ia berkata:
“Jadi seakan-akan diperlambangkan dari tumpang karang ing wiji iku mau, iku sik nang kono teka loro, dadi antara lanang wadon, jadi bukan hanya manusia, tapi binatang pun jantan dan betina, terus tumbuh-tumbuhan juga begitu ana lanang e ana wedok e, sehingga tumpang karang ing wiji iku mau kudu bebesanan karo wong loro”. (Wawancara 22 Agustus 2021)
(Jadi seakan-akan diperlambangkan dari tumpang karang ing wiji itu tadi, itu yang di sana ada dua, jadi antara laki-laki dan perempuan, bukan hanya manusia, tapi binatang pun jantan dan betina, terus tumbuh-tumbuhan juga begitu ada laki-laki dan perempuan, sehingga tumpang karang ing wiji itu tadi harus bebesanan dengan dua orang).

Gambar 2. Dua laki-laki menarikan tari Sodoran dengan mengangkat satu jari ke atas
(Dokumentasi penulis)
Pemaknaan tari Sodoran tidak berhenti di situ saja. Sebelum membawa tombak, mereka biasanya menari dengan memutar dan meliukkan satu jari ke atas secara ajeg dengan diiringi bunyi gamelan. Gerakan ini melambangkan keesaan Sang Hyang Widi Wasa. Di sisi lain, sekalipun mereka memeluk agama Hindu yang baru masuk di Tengger sekitar tahun 1978, berdasarkan penuturan Pak Suyitno selaku dukun Desa Jetak, namun mereka tetap menjalankan adat mereka. Dengan kata lain, agama Hindu dan adat Tengger pun berjalan dalam irama yang beriringan.

Gambar 3. Perempuan Tengger mengirim makan siang untuk peserta tari Sodoran
(Dokumentasi penulis)
Selepas babak bebesanan, penulis pun turut serta bersama perempuan lainnya untuk bergabung ke dalam aula dengan membawakan rantang berisikan makan siang berupa ketan, abon, klepon, telur asin, dan buah. Tidak jarang mereka saling bertukar makanan. Makanan yang larut dalam tubuh mereka rupanya juga menumbuhkan pertalian kekerabatan. Ini seperti halnya dijelaskan oleh Pak Sawi sebagai berikut:
“Jadi kita membayangkan satu keluarga di satu ruangan balai desa itu pesertanya itu dari macem-macem yang intinya itu dari Ngadisari, Wonotoro, Jetak. Itu peserta utama, yaitu melakukan tarian mewujudkan satu ikatan batin…unik sekali! Jadi uniknya itu apa ya, seakan-akan itu suatu tarian justru ada didikan untuk mempersatukan masyarakat umat begitu lho”. (Wawancara 22 Agustus 2021)
Momen makan bersama sebenarnya merepresentasikan kehidupan masyarakat Tengger yang kental dengan kebiasaan berbagi dan menjaga keterhubungan dengan sesama kerabatnya. Ada ikatan melampaui hubungan darah yang ditumbuhkan melalui proses tersebut. Dalam momen itu juga, berbagai kecemburuan maupun kesenjangan sosial dan ekonomi melebur. Mereka saling memandang sebagai kerabat yang setara. Nilai-nilai esensial yang menghidupkan kembali hakikat diri manusia sebagai makhluk sosial ini lah yang seharusnya ditransfer pada lebih banyak orang yang mana kerap tenggelam dalam individualisme.

Gambar 4. Masyarakat Tengger berkumpul menjelang acara makan bersama
(Dokumentasi penulis)
Tari Sodoran sebagai kearifan lokal masyarakat Tengger mampu menjadi wisata kultural baru yang kaya akan pengetahuan. Memang ada nilai kesakralan yang terkandung dalam tari Sodoran. Namun pada batas-batas tertentu, masyarakat pun menghendaki keterbukaan. Ada perasaan bangga ketika budaya mereka dikenal dan dilestarikan oleh lebih banyak orang. Dalam wawancara penulis dengan Pak Dukun, ia menjelaskan sebagai berikut:
“Ini (ritual Karo dan tari Sodoran) tidak bisa tertutup, mana mungkin manusia memberikan makna pada karo tersebut. Ya memang harus tahu. Kalau tertutup, manusia menutup apa yang kita lakukan ini kan malah kepentingan dirinya sendiri. Bukan kepentingan umum. Ini kan kepentingan umum untuk upacara ini. Sarana apapun, kapanpun waktunya ya terbuka.” (Wawancara 3 September 2021)
Pak Sawi selaku sesepuh desa pun membenarkan pernyataan Pak Dukun. Bahwasannya akan menjadi kesalahpahaman jika tari Sodoran dianggap sebagai acara eksklusif umat Hindu Tengger. Tari Sodoran dipahami dengan lebih baik sebagai adat Tengger yang mana sifatnya terbuka untuk disaksikan umum. Walaupun sekali lagi perlu penulis tegaskan ada batas-batas kesakralan yang perlu dijaga. Apa yang dipertanyakan selanjutnya ialah tentang pengembangan tari Sodoran sebagai wisata kultural yang tepat.
Dalam mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan tentu membutuhkan kerja sama antara berbagai pihak, terutama masyarakat Tengger dan pemerintah. Pertama, kesadaran akan potensi kearifan lokal tari Sodoran sebagai potensi wisata perlu ditumbuhkan. Partisipasi masyarakat pun dibutuhkan. Tentunya partisipasi yang dimaksud bukan hanya di kalangan elit, melainkan juga seluruh lapisan masyarakat. Salah satu wadah yang bisa dimanfaatkan adalah menghidupkan kembali Pokdarwis Tengger (Kelompok Sadar Wisata) yang sudah lama menonaktifkan diri. Baru setelahnya secara bersama-bersama, mereka dapat merumuskan tujuan pariwisata dengan jelas. Dalam hal ini keterwakilan suara setiap lapisan masyarakat Tengger perlu diperhatikan. Langkah selanjutnya ialah membangun kepercayaan di antara satu dengan yang lain. Terakhir, sentuhan framing media massa dan promosi di ruang digital dapat menarik perhatian. Memang dalam prosesnya, masyarakat dituntut untuk kreatif dan memperluas resonansi keunikan kearifan lokal mereka melalui adaptasi perkembangan teknologi.
Selain dari masyarakat, pemerintah juga punya tanggung jawab besar dalam program pengembangan wisata, misalnya saja dalam pembuatan kebijakan. Tidak bisa dipungkiri bahwa kebijakan pariwisata berpengaruh dalam penentuan bentuk dan tujuan destinasi wisata. Di sisi lain, pemerintah bukan hanya bertugas memberi dana insentif tapi juga harus tahu apa yang dibutuhkan masyarakat. Dengan kata lain, pemerintah seharusnya konsisten dan gigih mendampingi masyarakat. Walaupun aktualisasi gambaran ini terdengar tidak mudah, tetapi perlu dipahami juga bahwa memang butuh waktu yang lama untuk membimbing masyarakat dalam tataran wisata berkelanjutan. Namun, dibanding memberi bantuan yang sifatnya sementara dan destruktif, maka tidak ada salahnya mengambil langkah perlahan dan berkelanjutan.
Sebagai penutup, penulis akan memulai dengan fakta yang tampaknya diamini banyak orang bahwa bumi Tengger bukan hanya dilimpahi sumber daya alam, melainkan juga kaya akan keberagaman budaya. Sejauh ini, masyarakat Tengger masih bergantung dengan wisata TNBTS untuk dapat bertahan hidup. Padahal peran mereka dalam pengembangan wisata tersebut cukup monoton dan minor. Di sisi lain, pemahaman konsep TNBTS sebagai kawasan konservasi yang patut dijauhkan dari tindakan eksploitasi seharusnya mendorong masyarakat Tengger untuk mengembangkan model pariwisata berkelanjutan yang baru. Tidak dapat dipungkiri pula bahwa kondisi lingkungan yang tidak menentu menuntut mereka untuk lebih adaptif dalam menghadapi perkembangan zaman.
Melalui tulisan ini, penulis mengusulkan dibentuknya wisata berkelanjutan dengan memanfaatkan kearifan lokal. Sebagai penganut agama Hindu yang juga menjalankan adat, masyarakat Tengger memiliki kearifan lokal berupa tari Sodoran. Dalam tarian tersebut terdapat beragam pemaknaan. Mulai dari berbagai gerakan tarian yang merepresentasikan keesaan ketuhanan, tumbuhnya manusia berserta jalinan kekerabatan, serta kebersamaan yang menguraikan kesenjangan ekonomi, sosial, dan budaya. Tari Sodoran mampu menghubungkan masyarakat Tengger dengan Tuhan maupun dengan sesama kerabat. Pada akhirnya keseimbangan dan keharmonisan dalam menjalankan hidup rukun pun terbingkai dengan baik melalui tarian tersebut. Nilai-nilai esensial ini yang menjadi cikal bakal dibangunnya pariwisata yang menciptakan pengalaman kultural dengan kesan yang membekas pada setiap wisatawan.
Dalam mewujudkan tari Sodoran sebagai wisata berkelanjutan, dibutuhkan kerja sama dari masyarakat dan pemerintah. Pengembangan model wisata bottom up yang melibatkan partisipasi masyarakat diharapkan menjadikan mereka lebih mandiri. Guna merealisasikan ini, masyarakat harus bahu membahu membentuk tujuan wisata, mengembangkannya, dan secara kreatif mengumandangkan keunikan budaya mereka. Mereka dapat memanfaatkan media digital untuk mentransfer nilai-nilai kearifan lokal. Ini sekaligus menjadi strategi untuk melestarikan adat tanpa menutup mata akan kemajuan teknologi.
Pengembangan wisata ini tentunya membutuhkan dukungan dari pemerintah. Perencanaan dan kebijakan pariwisata memegang peran signifikan dalam pemberdayaan masyarakat sebagai aktor dominan dalam proses ini. Fasilitas yang memadai dan bimbingan yang tepat diperlukan oleh masyarakat Tengger. Sinkronisasi gerak antara masyarakat dan pemerintah dalam mengembangkan kearifan lokal pada akhirnya diharapkan menjadi alternatif solusi yang menjanjikan. Ini layaknya filosofi sodor dalam tari Sodoran bahwa ketika mencapai satu tujuan, ada banyak jalan yang bisa ditempuh. Sama halnya dalam mencapai masyarakat Tengger yang sejahtera sekaligus tetap menjaga keasrian Gunung Bromo, ada berbagai cara yang dapat dilakukan.
Penulis :Yayuk Windarti
Juara 3 Kategori Mahasiswa