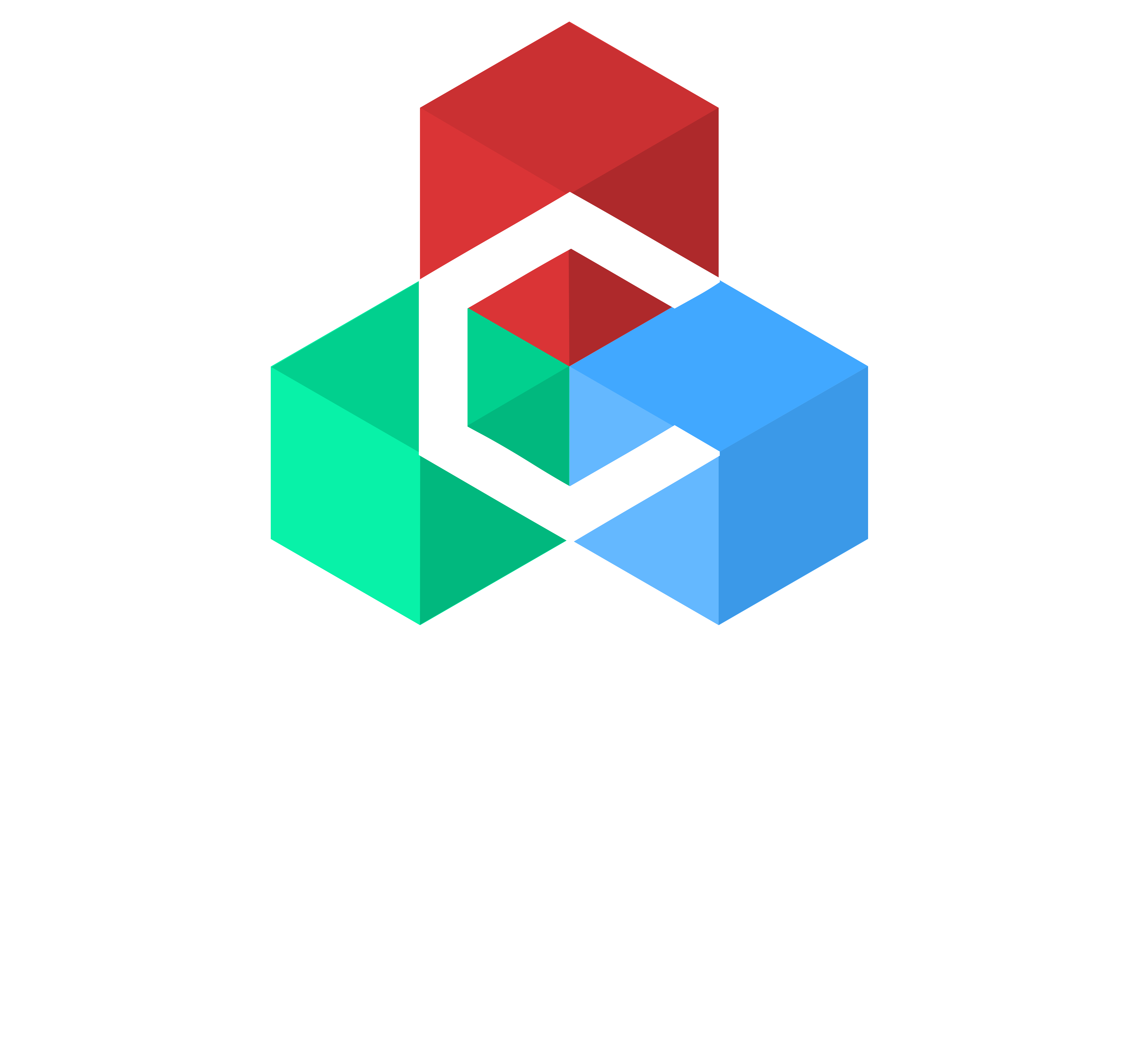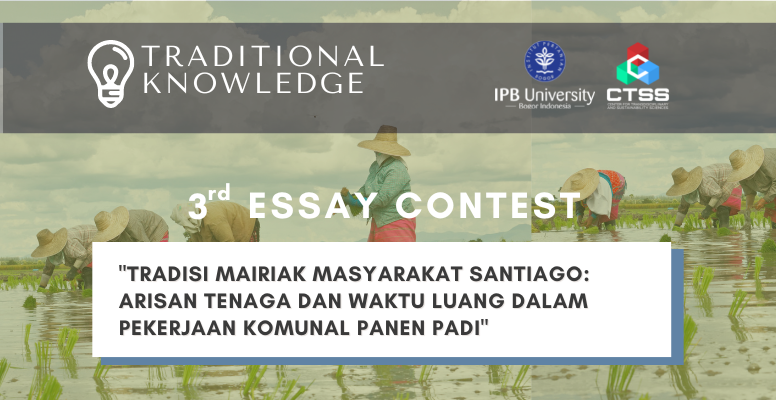“Tambuah Ciek, Da!” Kalimat ini harusnya sudah tidak asing lagi ditelinga masyarakat kita. Siapa yang tidak tahu Nasi Padang? Kuliner yang disukai hampir seluruh lidah masyarakat Indonesia tersaji di restoran, rumah makan sampai ampera-ampera pinggir jalan. Berdasarkan penelitian sejarah terungkap bahwa tersebarnya rumah makan yang menyediakan masakan khas Minang tersebut ke berbagai penjuru Nusantara dan dunia, bermula dari peristiwa PRRI (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia) tahun 1958, konflik politik dan perang saudara yang berkecamuk di Sumatera Tengah (Sumatera Barat) hingga menyebabkan sebagian besar komunitas Minangkabau memilih untuk merantau meninggalkan tanah kelahiran, menetap di wilayah baru dan kemudian mendirikan usaha rumah makan.
Nasi Padang merupakan kombinasi antara nasi, lauk-pauk, sayur, sambel dan kuah santal kental dengan cita rasa khas gurih dan pedas yang begitu menggugah selera. Nasi Padang jadi makanan sejuta umat. Ada sedikir rahasia yang belum banyak diketahui bahwa rasanya bisa begitu maksimal ternyata bukan sekedar karena bumbu kaya rempah atau perpaduan komposisi ternyata juga pengaruh dari pemilihan beras, bahwa tidak semua nasi cocok untuk sajian ini. Agar bisa “mengawinkan” rasa mesti menggunakan beras yang pulen, lembut dan taburai (tidak menggumpal), ciri-ciri ini terdapat pada jenis bareh Solok (beras Solok). Sesuai namanya beras berjenis long grain (bulir lonjong-memanjang) ini memang berasal dan ditanam di wilayah Solok, Sumatera Barat, cocok untuk Nasi Padang karena mengeluarkan aroma harum dan tidak cepat lembek saat terkena kuah.
Beras Solok terdiri dari dua varietas yaitu Sokan dan Anak Daro adalah jaminan kualitas telah pula tersertifikasi, Indikasi Geografis (IG). Untuk harga memang lebih mahal di atas rata-rata harga beras yang umumnya. Kendati demikian tapi tetap banyak yang mencari bukan hanya di lokal, Indonesia bahkan sampai luar negeri. Beras ini juga ditasbihkan menjadi ikon dan komoditi kebanggaan masyarakat Solok yang kemudian disematkan menjadi nama terminal, Terminal Bareh Solok. Jauh sebelum itu Nuskan Sjarif, seniman serba bisa era 60an pernah pula menuangkan “rasa” tersebut ke dalam lagu ciptaannya berjudul “Bareh Solok” yang populer dinyanyikan Elly Kasim.
Kabupaten Solok termasuk salah satu sentra produksi beras nasional, sebagian besar masyarakat di sana memang hidup sebagai petani padi. Membentang areal persawahan yang luasnya tak kurang dari 52 ribu hektar. Wajar bila mulai terbesit pertanyaan bagaimana Bareh Solok bisa sebegitu masyhurnya? Apakah ada keterkaitan antara bibit, kondisi tanah, perairan atau cara cocok-tanamnya? Sementara mencari jawaban ternyata ada yang menjadi kerisauan dan permasalahan dari banyak pihak, soal mulai meredupnya pamor dan tak banyak lagi petani di wilayah Solok yang bertani padi ini, walaupun masuk varietas padi unggul lokal. Alasannya pertanian padi jenis ini cocoknya ditanam secara organik, namun yang tak bisa dihindari tidak mudah bertanam padi organik butuh ketelitian, pilihan bibit mesti berkualitas dengan masa panen yang cenderung lebih lama dan hasil yang lebih sedikit. Secara rasional demi mengejar keuntungan ekonomi dan meminimalisir resiko tentu petani cenderung akam memilih mengusahakan padi anorganik.
Pada suatu daerah yang seringkali disebut sebagai Santiago, tapi ini bukan Santiago de Chile, kota terbesar di Chili, Amerika Latin dan bukan pula Santiago Bernabéu, stadion milik raksasa sepak bola Real Madrid FC di Madrid, Spanyol. Nagari Santiago (Sariak Alahan Tigo), Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok-Sumatera Barat. Nagari yang dilintasi sungai Batang Gumanti dengan bentang alam berupa berbukit dan lereng gunung ini istimewa sawah-sawah menghampar luas. Masyarakat Nagari Santiago sejak dulu memang petani padi-sawah, yang menjadikan urusan turun ke sawah bukan sekadar sebagai mata pencaharian namun juga bagian dari budaya yang sarat nilai-nilai. Ada yang proses budidaya padi yang berbeda dari kebanyakan wilayah lain karena masih mengolah sawah secara manual dan dilakukan secara komunal, mulai dari proses tanam hingga panen.
Mengapa masyarakat Nagari Santiago dan beberapa daerah lain di Solok tak tergiur dengan rasionalisasi pragmatis bertanama padi anorganik? Apakah mereka melakukan ini atas dasar internalisasi aktivitas budaya dan upaya untuk terus menghidupkan pengetahuan lokal mereka, sehingga rela untuk lebih bersusah-susah. Apakah sesuatu yang dianggap sulit ketika dikerjakan sendiri akan sama sulitnya jika dikerjakan bersama? Barangkali di sini letak jawabannya. Masyarakat Nagari Santiago menjadi contoh kongkret ketika berada dalam gempuran zaman yang berubah namun secara komunal tetap berupaya memberdayakan kearifan lokalnya (local wisdom) agar tak usang, lapuk, atau jadi sia-sia tanpa kegunaan.
Kenangan Tentang Lampu Stromking
Suatu hari lepas senja, ketika sedang di daerah Bogor, saya diajak beberapa teman untuk mengunjungi sebuah kedai kopi kecil yang ada di kaki Gunung Salak. Kami ingin menikmati kentalnya aroma kaki bersama heningnya suasana gunung. Suasannya begitu luar biasa, ketika itu saya mendapati sesuatu yang sudah belasan atau bahkan hampir hitungan puluh tahun tak saya temui, yaitu terangnya pancaran sinar lampu petromak. Walaupun sudah dialiri listrik kedai kopi tersebut pada beberapa titik tetap menyalakan lampu minyak tersebut demi mendapatkan suasana dan nostalgia para pengunjung.
Benar saja, mujarab seketika ingatan membawa saya kembali pada masa kanak-kanak, ketika di ranah Minang, Sumatera Barat. Desa-desa (sekarang nagari) yang masih minim dialiri penerangan listrik sehingga untuk penerangan saat malam hari masyarakat menggunakan sumber pencahayaan lampu togok atau lampu sentir, bercahaya kuning-redup. Sedikit saja rumah-rumah yang cahaya lebih terang karena menggunakan lampu petromak, karena tidak semua sanggup memilikinya. Masa kecil tersebut menjadi lebih takjub lagi ketika diwaktu-waktu tertentu mendapati lampu-lampu tersebut menyala di tengah areal sawah, orang di nagari menyebutnya lampu stromking, berasal dari bahasa Belanda. Lampu dengan bakar minyak tanah bertekanan ini terang nyalanya mendekati cahaya lampu led listrik.
Apa yang dilakukan para petani ranah Minang pada malam hari dengan menggunakan lampu stromking ini, memang sedikit janggal. Dimanapun umumnya aktivitas ke sawah itu dikerjakan dari pagi hingga menjelang siang hari, jika pun malam itu hanya sekedar memeriksa bandar (saluran) air yang cukup dilakukan satu atau dua orang saja. Pada momen tertentu, seringkali setiap masa panen sejak beberapa dekade lalu jamak ditemui secara berkelompok para petani padi sawah di Sumatera Barat yang bekerja semalam suntuk, hingga menjelang dini hari. Itulah yang kemudian saya ketahui sebagai tradisi Mairiak.
Masyarakat Minangkabau yang menganut budaya matrilineal sejak zaman nenek moyang juga memang sudah indentik sebagai masyarakat agraris. Di balik itu ternyata banyak menyimpan kekayaan budaya-tradisi yang sifatnya komunal yaitu masyarakat yang hidup dalam kelompok-kelompok seperti: tradisi Surau, tradisi Lapau. Begitu juga dengan urusan pekerjaan, mata pencaharian sebagai petani, dimana ketika itu masyarakat Minang memposisikan sawah bukan hanya sebagai lahan garapan untuk sumber pangan atau pendapatan ekonomi semata. Ada banyak aktivitas komunal yang sarat nilai budaya di balik aktivitas ke sawah satu di antaranya ialah tradisi Mairiak. Tradisi Mairiak jadi menarik untuk diketengahkan, selain masih minim bahasan ternyata sudah sangat jarang ditemui bahkan nyaris hilang (punah).
Akan lebih mencerahkan ketika mampu mengaitkannya dengan kebutuhan pembangunan yang bersifat nasional ataupun global, seperti misalnya konsep pembangunan SDGs. Jika dikaji dari SDGs ini tak berlebihan jika menyatakan tradisi Mairiak menjadi sesuatu yang kembali baru. Kebaharuan itu dalam arti tradisi yang dulunya eksis kemudian tersisih dalam perjalanan waktu, perubahan ruang, dan teralihkan ragam peristiwa namun, kini kembali mendapatkan urgensi untuk kembali digali nilai-nilai adiluhungnya guna memperkuat dan merekat kemitraan global seperti halnya pembangunan berkelanjutan berbasis SDGs. Ini jadi jawaban bagaimana pengetahuan lokal menjadi jalan untuk penerapan SDGs.
Pekerjaan utama kita sekarang ialah menggali pengetahuan dan mengembalikan ingatan kolektif tradisi Mairiak ke alam pikir generasi muda sebagai subjek pembangunan. Dulunya tradisi Mairiak memang tersebar hampir diseluruh nagari. Mulai berangsur ditinggalkan ketika digalakkannya modernisasi “revolusi hijau” di bidang pertanian pada dekade 1980-an. Saat ini bahkan nyaris tak ada lagi berdasarkan pertimbangan efektifitas dan waktu kerja, efisiensi (privatisasi) tenaga, nilai ekonomi dan modernisasi teknologi pertanian menjadikan tradisi ini semakin hilang bersama lenyapnya sawah-sawah milik kaum. Setidaknya sekarang sudah diganti dengan yang semi-modern, yaitu “malambuik” sebagai untuk merontokan gabah dengan mesin perontok gabah atau mesin kipas (power treiser).
Mairiak: Antara Iuran Tenaga dan Pengisi Waktu Luang
Mairiak berasal dari kata “iriak” yang sama artinya memisahkan bulir padi dari tangkainya. Dilakukan secara manual dengan menginjak-injaknya menggunakan kaki. Pada beberapa tempat disebut baronde atau batobo yang artinya bergantian dan bergotong-royong. Benar bahwa ini adalah pekerjaan saling bantu antar kaum kerabat ketika panen padi. Tradisi sudah sangat tua diyakini telah ada sejak masyarakat Minangkabau mengenal bercocok tanam di sawah. Inti dari tradisi Mairiak ini merupakan panen yang dilakukan secara berganti-gantian secara giliran, setiap orang dengan kerelaan saling bantu ketika pemilik sawah atau penggarap sawah panen. Menjadi semakin istimewa karena para pairiak ini bekerja tanpa menerima upah berupa materi, seringkali upahnya berupa bagi hasil pertanian.
Secara lebih sederhana cara kerjanya ada kemiripan dengan budaya atau tradisi arisan ibu-ibu atau di Jawa ada tradisi Jimpitan yang tergabung karena adanya kesamaan visi, misi, kebutuhan, dan karakter. Begitu juga pada tradisi Mairiak, prinsipnya sama dari kita untuk kita. Hanya sedikit perbedaannya jika pada arisan umumnya yang dijadikan komoditas berupa uang, emas, barang berharga atau beras sejimpit. Namun pada tradisi Mairiak yang digilirkan secara berulang di sini bukan berupa benda material melainkan iuran berupa tenaga dan waktu luang. Hal ini awalnya dilakukan juga atas dasar pertimbangan praktis yaitu minimnya peralatan atau teknologi yang dapat digunakan untuk panen padi, sedangkan tenaga kerja banyak tersedia.
Kegiatan Mairiak ini terdiri dari tiga pertama fase pra Mairiak, ketika padi sudah siap panen maka akan dilakukan musyawarah keluarga yang dipimpin tungganai (penghulu kaum) berembuk untuk menentukan hari panen dan waktu Mairiak; kedua, pemberitahuan pada kerabat, bisanya cukup secara lisan saat bertemu atau dengan datang langsung ke masing-masing rumah; ketiga, menyabit padi, biasanya sudah ditentukan orang-orangnya atau dikerjakan kelompok kerja dari pemilik sawah; keempat, pembuatan lungguak, yang sering kali juga disiapkan bersama para panyabik (penyabit) dan kelima, persiapan peralatan.
Walaupun dikerjakan secara manual ternyata Mairiak juga memerlukan banyak persiapan dan peralatan, selain “lungguak” ada juga kebutuhan tungkek (tongkat) biasanya terbuat dari batang bambu, di mana masing-masing pangiriak memegang dua tungkek untuk bertumpu dan penahan beban tubuh agar tidak jatuh; lapiak (tikar) atau sering juga diganti terpal plastik yang digunakan sebagai alas mairiak; katidiang atau karung untuk tempat penampung bulir padi setelah di-iriak; lalu dangau (pondok) sederhana tanpa dinding dengan atap jerami sebagai tempat istirahat, sholat dan makan/minum.
Selain itu beberapa perbekalan yang tak boleh terlupa disiapakan yaitu: ransum atau makan dan minum (teh dan kopi), nasi dan lauk-pauknya untuk asupan tenaga tukang iriak beserta makanan ringan seperti nasi lemak (uduk), kolak, bubur, dan gorengan. Hal yang juga mesti ada yaitu alat bantu penerangan, lampu stromking, bisa milik sendiri atau pinjam inventaris nagari, lampu ini dibutuhkan nyalanya cukup terang, setidaknya butuh dua lampu. Pada beberapa pelaksana alek yang memiliki kemampuan ekonomi lebih agar lebih meriah menyertakan hiburan, kesenian randai atau talempong pacik.
Selanjutnya fase pelaksanaan Mairiak yang prinsipnya bisa siang atau malam hari. Namun seringkali dikerjakan malam, menjadi semakin unik karena di antara begitu banyak tradisi turun ke sawah, Mairiak inilah hampir jadi satu-satunya yang dilakukan malam hari., Disengajakan malam hari juga dengan alasan yang sangat logis yaitu dalam rangka “mencari hari berlebih” (waktu lebih luang) dan menghindari panas-terik Matahari, sehingga beban kerja jadi lebih ringan. Selain itu seringkali pagi hingga siang hari digunakan untuk kesibukan pribadi, menyabit dan membuat “lungguak” padi.
Mairiak dapat diikuti oleh seluruh kerabat sekaum, keluarga, kerabat dekat, termasuk kerabat dari pihak ipar-besan dari anak, menantu, saudara dan lain-lain. Jumlah orangnyanya bisa beragam tergantung jumlah kerabat dan luasnya sawah yang akan dipanen, umumnya antara 10-20 orang. Peserta Mairiak ini sebenarnya terdiri dari laki-laki dan perempuan. Hanya untuk pekerjaan utama hanya dilakukan oleh kaum laki-laki dewasa, umur 20 tahun ke atas. Sedangkan pihak perempuan menjadi pendukung, menyiapkan minum-kawa (semacam teh yang terbuat dari daun kopi) dan melaksanakan pekerjaan-pekerjan pasca Mairiak.
Padi yang sudah memasuki usia panen disabit (dipotong) lalu dikumpulkan di petak sawah yang memang disiapkan untuk tempat Mairiak, di malam harinya. Lokasi yang digunakan biasanya adalah sawah yang sudah selesai dipanen, dipilih yang tumpaknya paling luas dan datar dengan terlebih dahulu memangkas habis sisa batang padi hingga rata. Di sinilah lungguak atau kalungguak disiapkan berupa susunan tumpukan batang padi. Dalam sekali panen jika jumlanya banyak tinggi tumpukan “lungguak” ini bisa mencapai setinggi orang dewasa yang disusun dengan pola seperti huruf U atau O, tujuannya guna memudahkan proses Mairiak yang akan dikerjakan di depan tumpukan lungguak tersebut.
Selepas Isya, dengan seluruh peralatan yang sudah tertata termasuk penerangan lampu stromking, digantungkan pada kayu agar posisinya lebih tinggi sehingga dapat menerangi seluruh areal Mairiak. Para peserta satu persatu datang, sembari menunggu ramai di mulai dengan obrolan-obroloan ringan, sembari merokok. Lalu tanpa perlu ada yang memberi aba-aba mereka akan mulai mengambil tungkek dan batang padi yang telah teronggok dalam satu genggaman kecil. Biasanya dimulai dari datuak atau yang dituakan, sebagai wujud penghormatan dan menghargai kemudian diikuti yang lain.
Padi ditaruh di atas tikar atau terpal yang melantai di atas permukaan sawah. Tangan menggenggam erat ruas-ruas tungkek bambu yang menjadi pegangan. Kaki-kaki kekar dan lincah tersebut mulai bekerja dengan ritme memilin onggokan demi ongokan padi hingga rurut lepas dari tangkainya, menebar di atas tikar pandan. Walaupun hanya menggunakan kaki (telapak) dan tungkek, pekerjaan Mairiak ini bukanlah pekerjaan mudah, memerlukan keahlian dan kebiasaan agar lancar mengerjakannya. Keterampilan itu biasanya diperoleh secara otodidak dengan mencoba dan mengamati yang lebih senior yang melakukan. Jika Mairiak dikerjakan oleh yang telah terbiasa, maka akan terasa mudah dan cepat selesai, hal tersebut juga karena kulit kaki sudah kuat (kapalan) dan tahan lebih lama saat mengerjakan. Sedangkan bagi yang baru belajar melakukan Mairiak maka akan sulit dan lambat, serta telapak kaki akan terasa sakit.
Keseluruhan proses Mairiak bisa berlangsung semalaman, seringkali baru selesai menjelang tengah malam. Setelah itu baru masuk fase ketiga, yaitu kegiatan mangirai (membersihkan sisa jerami di bulir padi), maangin (memisahkan antara gabah dengan nan-hampo-hampa), manampi memasukkan padi yang sudah besih ke katidiang atau karung hingga menjelang pagi dan keesokan harinya setelah terang baru mengangkut padi ke rumah yang punya alek. Sedangkan batang padi yang telah diambil gabahnya juga tidak terbuang begitu saja, bisa jadi pakan ternak atau diunggun (dibakar) untuk menambah kesuburan menjelang masa tanam berikutnya.
Keterhubungan Tradisi Mairiak dan SDGS
Apabila dimaknai lebih dalam tradisi Mairiak ini bukan sekadar aktifitas bersama memanen padi, ada fungsi sosial budaya yang dikandungnya, yaitu menyemai kebersamaan, kesetiakawanan sosial, jiwa gotong-royong dan masyarakat egaliter. Lebih dari itu juga berfungsi sebagai wahana perkuatan dan pertukaran sosial antar masyarakat yang kemudian mengkristal menjadi nilai dan pengetahuan yang kemudia layak untuk disodorkan untuk memenuhi kebutuhan SDGS demi mewujudkan masyaarakat global.
SDGs sebagai suatu rencana aksi global untuk dapat maju bersama (no-one left behind) yang telah disepakati, yang intinya terkait pembangunan berkelanjutan guna mencapai kesejahteraan masyarakat dan mengakhiri kemiskinan dengan tetap memperhatikan kualitas lingkungan hidup. Sebuah kata kunci yaitu akselerasi pembangunan yang inklusif dan seimbang (ekonomi, sosial, dan lingkungan).
Menempatkan Tradisi Mairiak dalam konteks SDGs, memilik kaitan amat erat dengan petuah dan ajaran filosofis masyarakat Minangkabau, yaitu Mambangkik Batang Tarandam mengangkat kembali pohon yang terendam (terbenam), secara makna berarti menumbuhkan kembali kejayaan masa lalu melalui warisan nilai-nilai dan budaya untuk masa sekarang.
Pengalian kembali tradisi Mairiak yang sarat akan nilai-nilai pembangunan holistik yang bukan saja melulu pertimbangan keuntungan ekonomi yang selama ini seringkali mengesampingkan dampak lingkungan namun di sini tersirat bagaimana orientasi pelestarian dan kelestarian bumi, sebagaimana yang dicita-citakan dalam SDGs untuk menjadikan bumi lebih damai, aman, dan sejahtera bagi seluruh warga dunia serta memastikan bermanfaat untuk kehidupan generasi mendatang.
Konsep SDGs ini diperlukan untuk memenuhi tujuan dan memberikan arahan (guidance) agenda pembangunan baru (global) dan berkelanjutan yang berdasarkan atas hak asasi manusia dan kesetaraan. Hal yang perlu kembali diingat prinsip SDGs ialah universal, integrasi dan inklusif, untuk meyakinkan bahwa tidak ada satupun yang tertinggal.
Setelah di atas kita uraikan tentang apa dan bagaimana tradisi Mairiak berlangsung sebagai bagian dari pengetahuan lokal, masyarakat Nagari Santiago. Dari karakter dan ciri-ciri yang terkandung maka tidak berlebihan jika dinyatakan bahwa sebagian besar tujuan dari SDGs tersebut dapat terpenuhi. Implementasi tradisi Mairiak sebagai kerja gotong-royong masyarakat sangat erat kaitannya dengan urusan ketahanan pangan secara langsung dapat menyasar pemenuhan 14 dari 17 tujuan SDGs, guna mewujudkan kemaslahatan umum secara global yang: (1) terbebas dari kemiskinan; (2) terbebas dari kelaparan; (3) kehidupan sehat dan sejahtera; (4) kesetaraan gender; (5) energi bersih dan terjangkau; (6) pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi; (7) industri, inovasi dan infrastruktur; (8) berkurangnya kesenjangan; (9) kota dan komunitas berkelanjutan; (10) konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab; (11) penanganan perubahan iklim; (12) ekosistem darat; (13) perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh; dan (14) kemitraan untuk mencapai tujuan.
Dari uraian tentang di atas kita bisa melihat bagaimana benang merah dan pemahamana antara tradisi Mairiak dan SDGs bahwa kunci suksesnyaterletak pada aspek kebersamaan dan keikutsertaan mendukung program dalam lingkup global. Penggalian kearifan lokal (local wisdom) menjadi pengetahuan lokal sama dengan menjemput kembali nilai-nilai karakter, jati diri bangsa dan praktik budaya kerja komunal menjadi sangat diperlukan sebagai strategi dan modal untuk menyelesaikan persoalan lokal, nasional dan bahkan global, seperti kesepakatan SDGs guna mencapai kemaslahatan umum (bene commune).
Tradisi Mairiak dalam kontek pembangunan berkelanjutan juga jadi semacam bentuk perlawanan terhadap hegemoni kapitalis, yang menilai segala sesuatu atas dasar kepemilikan modal. Dalam pelaksanaan Mairiak tak mengenal uang, pengupahan kerja yang dinilai tidak didasarkan nilai nominal uang semata, di balik ini ada ruang sosialisasi, berdialektika dan saling tukar informasi. Ini penting karena merupakan bagian dari jatidiri bangsa yang sangat menjunjung harga diri secara bermartabat. Hal ini tercermin dalam ajaran masyarakat Minangkabau “malawan dunia urang” (melawan dunia orang –individualisme dan kapitalisme).
Tradisi Mairiak terbukti berperan memperkuat persatuan dan kesatuan komunitas, perasaan saling membutuhkan dan harapan bantuan dengan tujuan agar pekerjaan dapat selesai dengan baik dan cepat. Malinowski, sebut sebagai aktifitas yang menimbulkan kewajiban membalas atau prinsip timbal balik (principle of recipprocity) atau yang kita pahami sebagai, menekankan semangat gotong-royong mengolah lahan pertanian. Seperti yang Homans sebut sebagai teori Pertukaran Sosial, dalam hubungan sosial terdapat unsur ganjaran, pengorbanan, dan keuntungan yang saling mempengaruhi.
Urgensi Menginternalisai Tradisi Mairiak dalam SDGs
Suatu keniscayaan bahwa pengetahuan berkembang dinamis, ada begitu banyak serakan pengetahuan lokal (berbasis pengalaman dan budaya) di Nusantara ini yang mesti digali dan temukan kembali untuk dikawinkan dengan pengetahuan modern (berbasis rasio) guna menghasilkan sains keberlanjutan (sustainability science). Sehingga dapat jadi strategi dan solusi untuk mengatasi berbagai persoalan global yang telah ada depan mata. Sekaligus jadi upaya kita memastikan akan bisa mewariskan keberlanjutan kehidupan bagi anak-cucu.
Kita tentu tidak ingin kehilangan pengetahuan lokal yang terkandung dalam tradisi Mairiak, ada kewajiban mewujudkan SDGs yang sesungguhnya kita bisa cicil dengan menyematkannya pada tradisi Mairiak yang perlu untuk terus digaungkan maka akan hilang bersamaan dengan tandasnya sawah-sawah yang telah berubah fungsi menjadi pemukiman atau sentra ekonomi lainnya. Tradisi Mairiak semakin menegaskan bagaimana kayanya negeri kita dengan nilai kebersamaan sebagai kekayaan budaya yang dibangun berdasarkan filosofi dan pengetahuan “alam takambang jadi guru” yang diimplementasikan berbasis kegiatan komunal masyarakat Minangkabau. Dimana nilai-nilai luhur yang terkandung mesti dilestarikan agar tetap dikenal oleh generasi sekarang dan yang akan datang.
Kompleknya permasalahan (wicked problem) di tengah kian terpinggirkannya praktik budaya, adat-istiadat, pengetahuan lokal yang tengah berhadap-hadapan dengan arus modernisasi, bahwa siapa yang kuat maka dia yang akan bertahan. Dengan menghidupkan kembali praktik mairiak dalam aktivitas produksi komunal dapat jadi benteng terakhir yang akan memperkuat masyarakat agar tak terpelanting kedalam keusangan dan terjerumus kedalam lubang kejahiliahan modern. Memberikan harapan kebersamaan masyarakat Solok untuk kembali bertanam padi Sokan dan Anak Daro sebagai bentuk langkah kemitraan untuk mencapai tujuan (SDGs) mewujudkan cita-cita Kabupaten Solok menjadi lumbung padi Nasional dengan komoditas andalan bareh Solok. Untuk kemudian direplikasi pada banyak tempat sesuai kekhasan, hingga terwujud kehidupan tanpa kemiskinan dan tanpa kelaparan. Masa depan kita bisa cari di dalam masa lalu!
Penulis : Purwanto Putra
Juara 2 Kategori Umum