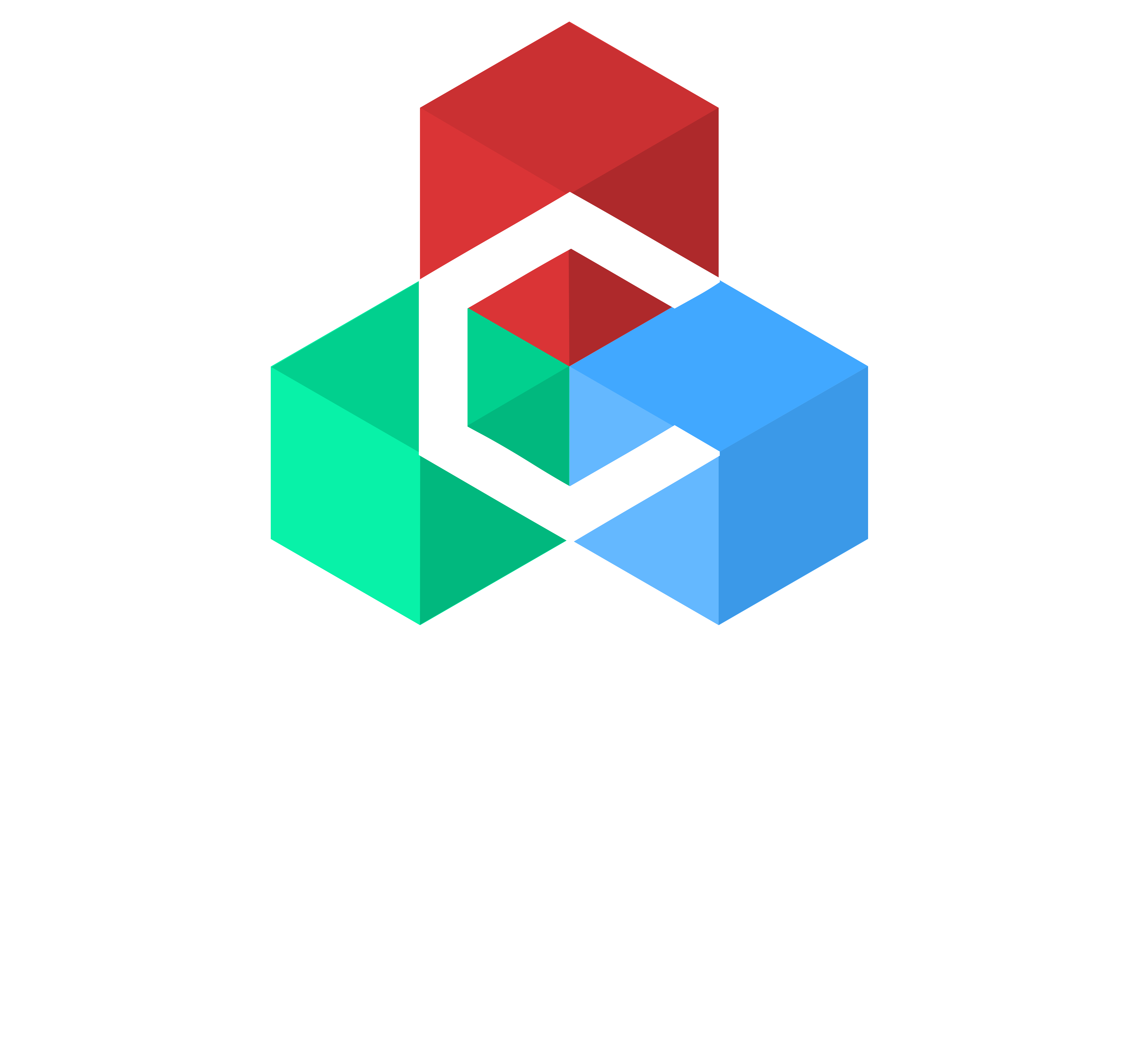Gizi sebagai Praktik Kebudayaan
Dibalik makanan terselip kisah panjang tentang kekuasaan, nilai budaya dan makna hidup yang jarang disadari. Makan bergizi bukan sekedar soal kalori, protein dan angka dalam tabel gizi, ia adalah cermin kebudayaan yang memantulkan siapa kita, bagaimana kita hidup dan kemana arah peradaban ini bergerak. Apa yang kita makan, dari mana berasal, siapa yang menyiapkannya dan bagaimana disajikan, semuanya adalah ekspresi dari tatanan sosial dan nilai-nilai yang kita anut.
Dalam perspektif kebudayaan, pemenuhan gizi terkait dengan nilai, ritus dan makna. Di banyak komunitas adat dan masyarakat tradisional, makanan tidak pernah netral. Ia selalu hadir dalam konteks. Nasi tidak hanya sekedar karbohidrat tetapi lambang kehidupan. Air kelapa bukan cairan penyegar namun simbol kesucian. Pangan lokal seperti ubi, sagu dan ragam kacang-kacangan bukan sekedar sumber energi melainkan penanda identitas, pengetahuan ekologis dan kebanggaan lokal.
Krisis gizi saat ini bisa dipandang sebagai krisis kebudayaan. Reduksi makna dan komodifikasi gizi telah memutus hubungan antara pangan dan konteksnya. Anak-anak tidak lagi mengenal asal makanan mereka, mereka hanya tahu merek dan kemasan. Gizi kehilangan makna ketika berubah menjadi produk anonim dari sistem produksi massal. Negara ikut terlarut dalam logika yang sama, membangun program gizi bukan sebagai sarana edukasi nilai-nilai pangan, namun sebagai proyek politik yang diukur dengan angka distribusi dan persentase penyerapan anggaran.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah contoh bagaimana negara menjadi agensi reduksionisme makna gizi. Ia memandang gizi sebagai urusan teknis, makanan dikirim dari dapur industri, anak-anak diberi makan dan laporan diklaim berhasil. Tapi dibalik itu, hilanglah kebudayaan pangan. Anak-anak kehilangan kesempatan untuk belajar tentang makna pangan yang tumbuh dari tanah mereka berpijak. Sekolah-sekolah kehilangan makna sebagai tempat belajar budaya pangan, kini hanya menjadi titik distribusi kotak makanan. Gizi dalam bingkai ini menjadi alat pembentukan obyek baru: konsumen yang patuh, bukan warga yang sadar akan sumber pangannya.
Menempatkan gizi sebagai praktik kebudayaan, menuntut perubahan radikal, dari urusan mengisi perut menjadi urusan membentuk manusia. Pendidikan gizi adalah dasarnya adalah menghidupkan budaya pangan lintas generasi. Anak-anak diberi kesempatan belajar bahwa makan bergizi adalah bagian dari hidup bermasyarakat, nilai solidaritas dan moral, hingga kesadaran ekologis dan kecintaan pada kehidupan. Pendidikan gizi bukan sekadar kurikulum tambahan.
Filsuf pendidikan John Dewey pernah mengatakan bahwa pendidikan bukanlah persiapan untuk hidup, melainkan kehidupan itu sendiri. Maka, pendidikan gizi sejatinya bukan tentang menghafal piramida makanan atau menghitung kalori, melainkan tentang menghayati relasi antara pangan, manusia, dan bumi. Ia adalah praktik kebudayaan yang mengajarkan anak untuk peduli, untuk menanam, untuk berbagi, dan untuk memahami bahwa setiap butir nasi punya kisah panjang tentang tangan-tangan yang menanamnya.
Sekolah sebagai Persemaian Budaya Gizi
Hal ini membutuhkan lompatan paradigma, dari gizi sebagai proyek logistik menjadi proyek kebudayaan. Sekolah dapat menjadi pusat transformasi ini, sebagai ruang dimana kebudayaan pangan baru dibangun, sebagai arena dimana mengubah gizi dari sekedar urusan mengisi perut menjadi sebuah agenda transformasi hidup. Bagaimana sekolah bisa menjadi pusat transformasi kebudayaan gizi pangan?
Disinilah empat konsep inovasi peran sekolah dengan gizi sebagai praktik kebudayaan, penting untuk dihadirkan: school food lab, school food garden, school food hub, dan school food council.
School food lab (laboratorium pangan sekolah) menjadikan dunia anak sebagai ruang eksperimentasi dan inovasi budaya pangan. Di sana anak-anak belajar memasak, mengenal bahan lokal, dan menciptakan menu baru dari hasil bumi sekitar. Mereka belajar bahwa pangan bukan datang dari pabrik, tetapi dari alam yang harus dijaga. Guru mengintegrasikan pelajaran sains, seni, dan budaya lewat pangan. Di sini, gizi tidak diajarkan, tapi dihidupkan. Anak-anak menjadi ilmuwan kecil yang belajar bagaimana pangan bisa sehat, lezat, dan berkelanjutan.
School food garden (taman gizi sekolah) menjadi ruang praksis di mana anak menanam, memanen, dan memahami siklus hidup. Di dalamnya, guru gizi, guru IPA, dan orang tua bekerja sama membentuk pemahaman holistik tentang pangan. Dalam hal ini, bukan hanya kebun sekolah, namun usaha untuk menghidupkan ekosistem pangan sehat di sekolah secara luas, mencakup inovasi kantin sekolah. Kantin sekolah menjadi laboratorium cita rasa yang memanfaatkan hasil kebun. Komite gizi sekolah menggerakan seluruh elemen sekolah menjadi ekosistem produksi pangan sehat dan bernutrisi.
Lalu, school food hub (jejaring pangan sekolah) memperluas jaringan kebudayaan pangan ke luar sekolah. Sekolah menjadi simpul yang menghubungkan anak-anak dengan petani, nelayan, dan UMKM lokal. Anak belajar bahwa setiap makanan yang mereka makan memiliki tangan dan kisah di baliknya. Hub ini juga memperkuat ekonomi lokal, menjadikan konsumsi sebagai tindakan solidaritas sosial. Hub ini menciptakan rantai pasok pangan sehat dan berkeadilan, sekaligus memperkuat ekonomi lokal. Dengan begitu, setiap piring anak di sekolah juga menjadi alat redistribusi ekonomi, mengalirkan manfaat ke masyarakat di sekitarnya.
Akhirnya, school food council (dewan pangan sekolah) menghadirkan dimensi politik kebudayaan pangan: ruang deliberatif di mana sekolah, pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha merumuskan kebijakan bersama. Di sinilah seluruh pemangku kepentingan duduk bersama: pemerintah daerah, sekolah, guru, orang tua, petani, UMKM, dan komunitas. Dewan pangan sekolah ini bukan lembaga formal tambahan, melainkan platform demokratis untuk merancang, mengawasi, dan mengarahkan kebijakan pangan sekolah. Ia menjadi jembatan antara kebijakan dan kehidupan, antara sistem dan manusia. Lewat mekanisme ini, transparansi tumbuh, partisipasi dijamin, dan akuntabilitas dijaga.
Empat inovasi ini saling bertaut dalam satu ekosistem gizi yang hidup. Ia memulihkan hubungan yang hilang antara pengetahuan, praktik, dan kebudayaan. Anak-anak tidak hanya kenyang, tetapi juga paham. Mereka tidak hanya makan, tetapi juga menghargai. Sekolah tidak lagi menjadi tempat distribusi makanan, tetapi menjadi taman kebudayaan pangan, sebuah ruang dimana cita rasa, tanggung jawab, dan imajinasi masa depan dipupuk bersama.
Kritik terhadap MBG bukan sekadar lontaran teknis, tetapi penegasan filosofis: bahwa gizi tidak boleh dipisahkan dari kebudayaan. Sentralisme MBG hanyalah bentuk baru kolonialisme pangan, yang mengabaikan keragaman lokal dan mematikan kreativitas anak-anak. Gizi bukan proyek negara yang selesai dalam masa jabatan, melainkan proyek peradaban yang membentuk cara kita hidup, berpikir, dan berhubungan dengan dunia.
Gizi sebagai praktik kebudayaan adalah ajakan untuk mengembalikan makna makan sebagai tindakan bermoral dan beradab. MBG bukan salah niat, namun keliru dalam filosofi. Kita tidak membutuhkan lebih banyak proyek distribusi MBG, tetapi lebih banyak ruang belajar tentang kehidupan. Karena bangsa yang besar bukanlah bangsa yang sekadar kenyang, melainkan bangsa yang tahu mengapa dan bagaimana ia makan.
Kita perlu mengakhiri era di mana gizi dianggap sekadar proyek negara. Gizi harus menjadi gerakan kebudayaan, di mana sekolah menjadi simpul utama transformasi sosial. Karena sesungguhnya, memberi makan anak bukan hanya tentang memberi energi untuk hari ini, tetapi menghidupkan nilai untuk masa depan. Jika pendidikan adalah kehidupan itu sendiri, maka pendidikan gizi adalah cara kita menghidupkan budaya pangan yang lebih baik, untuk anak-anak, untuk bumi, dan untuk peradaban.
David Ardhian
Dewan Pakar pada Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP)